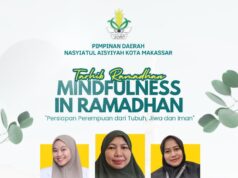(Pendekatan Artificial Intelligence)
Oleh : Safrin Salam*
Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia telah diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pengakuan oleh negara itu diatur dalam ketentuan Pasal 18 b ayat 2 yang mengatu bahwa : “Negara mengakui dan melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan zaman, prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang”.

Klausula Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 mengandung makna bahwa Negara mengakui Masyarakat Hukum Adat sepanjang memenuhi syarat negara dan diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud konstitusi itu adalah perlu adanya Undang-Undang Khusus yang mengatur masyarakat hukum adat. Saat ini, Undang-Undang tersebut masih dalam jelmaan RUU Masyarakat Hukum Adat. RUU yang masih dalam tahap pembahasan di DPR RI dengan Pemerintah (RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2021.
Seiring pembahasan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang masih dalam pembahasan. Negara kian menjadi frustasi dengan menerbitkan sejumlah Undang-Undang Sektoral yang mengatur pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Ketentuan UU Pengadaan tanah bagi kepentingan umum mengatur masyarakat hukum adat sebagai subjek penerima ganti rugi (Pasal 30). Begitu pula pada peraturan pelaksanaya yakni Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Perpres ini mengatur wilayah adat masuk dalam pendataan lokasi untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Pasal 17 ayat (2). Ketentuan hukum ini mengatur secara parsial tentang keberadaan masyarakat hukum adat pada wilayah subjek penerima ganti rugi dan pendataan lokasi wilayah ulayat. Pada ketentuan hukum yang lain terdapat Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Ketentuan hukum ini secara konkrit mengatur bentuk pengakuan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah Bupati/Walikota (Pasal 6 ayat 2).
Ketentuan-ketentuan hukum ini telah menggambarkan model pengakuan masyarakat hukum adat dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah. Namun seiring dengan perkembangan hukum, Negara kembali menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada klaster pengaturan tanah dan usahanya diatur pula mengenai Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan tanah dan usaha Perusahaan Swasta, Negara dan Masyarakat Hukum Adat diatur sedemikian berbeda konsep hukumnya.
Menurut analisis aplikasi Nvivo 12 Plus ditemukan bahwa Pada UU Cipta Kerja Pengakuan Masyarakat Hukum Adat diakui keberadaannya melalui peraturan perundang-undangan (Pasal 22 Klaster Usaha dan tanah). Namun pada pengaturan hak ulayat diatur dalam bentuk peraturan daerah (Pasal 9 Klaster Wilayah Pesisir). Ketentuan ini saling tumpang tindih dan tidak berlandaskan dari ketiga ketentuan hukum sebelumnya (UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Perpres dan Permendagri). Khususnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang bentuk hukum pengakuan negara adalah hanya dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah Bupati/Walikota/Gubernur.
Begitu pula dengan alih fungsi status tanah ulayat menjadi tanah negara atau lainnya. UU Cipta Kerja mengatur bahwa tanah ulayat bisa dialihkan status menjadi tanah negara atau tanah lainnya (HGB, HGU) melalui persetujuan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 86, Pasal 17). Jika perusahaan melanggar ketentuan hukum ini maka perusahaan hanya mendapatkan sanksi administratif. Pengaturan ini sejatinya mengambil konsep hukum yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Hal ini menunjukan ketimpangan pengaturan hukum tentang masyarakat hukum adat dan tanah ulayat.
Dengan keadaan demikian, maka temuan aplikasi Nvivo bahwa terjadi tumpang tindih antara pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat. UU Cipta kerja telah membuat norma hukum baru yang bermaksud merampas tanah ulayat dengan menggunakan sanksi administratif didalamnya. Konsep ini sejatinya telah dikenal dahulu pada zaman kolonial dengan nama Domein Verklaring : Negara dapat menguasai tanah adat sepanjang masyarakat hukum adat tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan secara tertulis. Kini perampasan tanah ulayat oleh negara hanya didasarkan tidak diakui masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum oleh negara.
Olehkarena itu diperlukan upaya pengujian konstitusi norma-norma didalamnya. Khususnya mengenai ketidakpastian bentuk pengakuan masyarakat hukum adat. Ketentuan ini perlu diubah dan disesuaikan dengan ketiga regulasi sebelumnya. Begitu pula dengan tanah ulayat yang penguasaannya bisa sewaktu-waktu dirampas oleh negara atau pun perusahaan swasta (Hanya menerima sanski administratif atau tidak diakui masyarakat hukum adat).
*) Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton