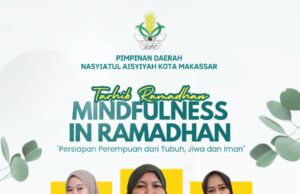Oleh : Asratillah*
Hingga tulisan ini dibuat, Majene dan Mamuju beberapa jam lalu kembali diguncang gempa tektonik dengan Magnitudo 5,2, lumayan terasa guncangannya, orang-orang pada panik, berdoa di beranda-beranda media sosial agar tetap selamat, dan tentunya memperparah kerusakan bangunan-bangunan yang telah dihantam getaran gempa beberapa kali sebelumnya. Tetapi yang perlu kita sadari, bahwa bukan hanya bangunan-bangunan kita yang rentan terhadap bencana (apakah gempa , longsor ataupun banjir), tetapi pulau Sulawesi itu sendiri adalah pulau yang memang rentan akan bencana-bencana geologis.
Armstrong F. Somprotan dalam Struktur Geologi Sulawesi (2012) menjelaskan dengan sederhana bahwa Sulawesi adalah pulau yang dirobek-robek oleh sesar (fault), rekahan (joint) dan perlipatan (folding) geologis. Daratan pejal yang kita injak bukanlah entitas yang stabil, tetapi merupakan sesuatu yang senantiasa bergerak dan mengalami perubahan-perubahan. Dan tentang ini mungkin sewaktu kita mendapatkan materi pengetahuan alam di bangku SMU, konon beratus-ratus juta tahun yang lalu (antara era Paleozoikum hingga Mesozoikum atau antara 300 hingga 200 juta tahun lalu) benua-benua di muka bumi bersatu dalam sebuah benua tunggal yang bernama Pangea, lalu karena proses geologis yang lambat tapi pasti terpecah menjadi benua-benua seperti yang kita kenal seperti saat ini.
Begitu pula dengan Sulawesi, dia bukanlah entitas sekali jadi, dia dulu tak nampak seperti saat ini, seperti huruf alphabet K besar di tengah-tengah kepulauan Nusantara, dia adalah buah dari sejumlah litologi (bebatuan) yang diseret-seret oleh peroses geologis. Armstrong F. Somprotan melabeli Sulawesi sebagai “daerah yang kompleks”. Darimana asal kompleksitas itu ?, karena Sulawesi adalah resultan dari tiga gerbong bebatuan (lempeng bumi) yang saling bertubrukan. Dari arah selatan bergeraklah lempeng Indo-Australia ke arah utara, dari arah timur ke barat bergeraklah lempeng pasifik dan ke arah tenggara bergeraklah lempeng Eurasia, di tambah satu lagi oleh lempeng mikro yang ukurannya lebih kecil yakni lempeng Filipina.
Tubrukan lempeng-lempeng tersebut, akhirnya memiliki empat lengan (mirip huruf K), Tetapi keempat lengan tersebut memiliki kondisi litologi (batuan), kandungan mineral, stratigrafi (perlapisan batuan) dan karakteristik paleontologis (sejarah makhlukh hidup yang pernah hidup) yang berbeda-beda pula. Namun bukan hanya itu, pulau Sulawesi juga dirobek-robek oleh sejumlah sesar-patahan. Kita mengenal sesar Palu Koro yang bisa bergeser dengan kecepatan hingga 44 mm per tahunnya (inilah sesar paling aktif di Sulawesi), dan kita ketahui telah memakan korban pada peristiwa tsunami dan likuifaksi di Palu beberapa tahun lampau. Ada sesar Matano yang memiliki kecepatan geser sebesar 37 mm per tahun, yang setelah gempa pertama dari rangkaian gempa di Sulbar kemarin, mengakibatkan gempa dengan magnitude 3 di sekitar Malili, Luwu Timur. Dan sesar-sesar yang lain seperti sesar Poso, sesar Lawanopo, sesar Walanae, Sesar Gorontalo termasuk sesar Mamuju yang diduga mengakibatkan gempa di daerah Majene dan Mamuju. Belum lagi sesar-sesar yang ukurannya lebih kecil. Anda bisa bayangkan bagaimana besarnya energi yang lepaskan dari dua blok batuan raksasa yang saling bergesekan ? dua buaa truk tronton yang saling bersenggolan di jalan raya, sudah cukup membuat kita terpingkal, apatah lagi jika berton-ton massa batuan saling beradu.
Sering ada yang bertanya, sampai kapan kita akan senantiasa diusik oleh gempa ? saya menjawab tidak ada yang tau pasti. Sebab dinamika geologis telah berlangsung sejak bermilyar tahun lalu jauh sebelum spesies Homo Sapiens bercokol di muka bumi (ada yang berpendapat Homo Sapiens pertama bercokol di Afrika sekitar 250.000 tahun lalu), dan menurut saya dinamika geologis akan tetap ada walaupun nantinya spesies manusia akan punah. Bukan hanya Sulawesi, seluruh wilayah Indonesia adalah daerah rentan akan bencana geologis. Menurut United States Geologiocal Survey (USGS), Indonesia berada di zona seismik yang sangat aktif dengan frekuensi gempa terbanyak kedua di dunia setelah Jepang. Apakah kita bisa menaklukkan bencana geologis ?, saya rasa tidak, yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dengannya.
Dalam biologi evolusi ada semacam adagium bahwa spesies yang bertahan hidup bukanlah spesies yang paling kuat, tetapi spesies yang paling mampu beradaptasi. Yang menjadi pertanyaan, sampai sejauh mana tata kelola negara kita adaptable dengan situasi geologis Indonesia ? sampai sejauh mana lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam penanganan bencana adaptable dengan situasi kebencanaan kita ? sampai sejauh mana penataan ruang kita adaptable dengan situasi kebencanaan ?.
Contoh kasus untuk Sulawesi Barat, para ahli geologi dan geofisika sebenarnya sudah melakukan pemetaan terhadap wilayah rawan gempa dan tsunami di daerah Sulawesi barat, dan sebagian wilayah Sulbar dinyatakan rentan akan keduanya karena beberapa variabel yang menjadi pertimbangan, mulai dari keberadaan sesar hingga kedalaman dan kecuraman lereng bawah laut. Semestinya pemerintah daerah dalam membuat rencana tata ruangnya, mesti mempertimbangkan hal-hal tersebut. Memprediksi kapan terjadinya gempa dan tsunami saat ini memang belum bisa, tetapi para ahli telah mampu (melalui simulasi komputer) mampu menghitung potensi besaran maksimal magnitudo gempa, dan kekuatan tsunami yang kemungkinan muncul, dan hal tersebut bisa dijadikan dasar dalam menata wilayah, mana kawasan pemukiman, mana kawasan perkantoran, dan mana kawasan yang hanya ditujukan sebagai jalur sistem transportasi dan destinasi wisata.
Selain itu, untuk pesisir pantai yang diperkirakan sebagai titik-titik berpotensi tsunami, bisa dilakukan penghijauan atau penananaman mangrove yang sedikit banyaknya bisa meredam energi gelombang tsunami bila terjadi. Dengan kata lain, bencana bukan hanya soal alam, tetapi dia juga terkait dengan kebijakan, terkait dengan keputusan-keputusan politik, terkait dengan orientasi ekonomi (apakah hanya berorientasi pertumbuhan ataukah keberlanjutan ?). Dan yang terakhir, pasca gempa di Sulbar, masyarakat yang terkena dampak mengeluhkan lambatnya upaya penanganan oleh pihak pemerintah setempat, dan ini menunjukkan birokrasi pemerintahan kita tidak siap untuk beradaptasi dengan resiko geologis yang telah menjadi “fitrah geologis” dari wilayah kerjanya. Tapi di satu sisi, untunglah etos charity masyarakat kita masih sangat kental walaupun disituasi pandemi, tetiba saja organisasi-organisasi sipil dan kemahasiswaan mengorganisasi diri dan mengambil inisiatif untuk menyalurkan bantuan kepada para korban, dan kepada mereka kita sangat berterima kasih.
*) Penulis adalah Direktur Profetik Institute on