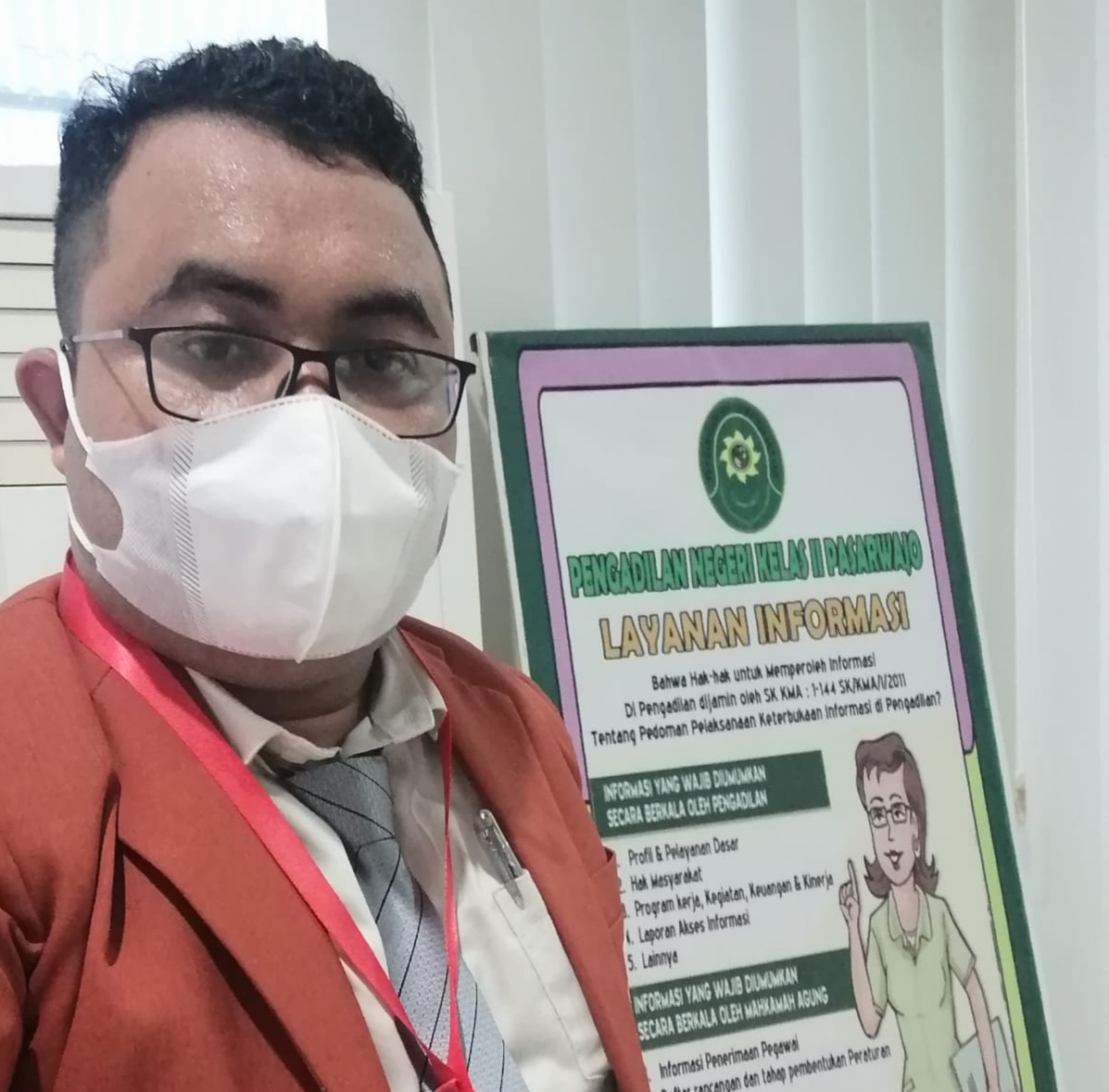Oleh : Safrin Salam, S.H., M.H*
Hakim dalam memutus sebuah perkara diberikan kebebasan sebesar-besarnya dalam memutus perkara. Kebebasan hakim dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Kebebasan itu tegas diatur dalam Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009. Secara filosofis makna pasal 3 adalah memberikan jaminan hakim dalam memutus perkara berdasarkan keyakinan dalam lubuk hatinya yang tertuang dalam putusan yang mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Idealnya, putusan hakim itu harus mencerminkan keadilan yang artinya bahwa putusan hakim harus berdasarkan keadilan yang sebesar-besarnya bagi para pihak bahkan putusan itu tidak boleh berat sebelah baik untuk Penggugat maupun Tergugat (Makna Yuridis Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009). Putusan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan demi keadilan cukup sulit diperoleh tatkala hakim diperhadapkan dengan sengketa hukum yang sifatnya belum diatur secara tegas diatur di dalam Undang-Undang. Salah satunya adalah sengketa tanah ulayat.
Sengketa tanah ulayat yang harusnya itu selesai pada ranah masyarakat hukum adat dengan hukum adat dipaksa untuk diperhadapkan dengan hukum negara melalui Pengadilan. Dipaksa dengan alasan oleh karena sengketa muncul bukan dari internal maupun masyarakat hukum adat tapi dari eksternal yakni negara atau perusahaan. Hal ini menjadikan posisi masyarakat hukum adat berhadapan dengan hukum negara melalui penyelesaian jalur pengadilan.
Keberadaan masyarakat hukum adat dalam kedudukan di pengadilan telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Jaminan perlindungan hukum masyarakat hukum adat dan hak-haknya pada ranah yang lebih sempit masih membutuhkan tafsiran-tafsiran hukum, salah satunya adalah bahwa untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dan hak-hak masyarakat hukum adat, keberadaannya harus diakui oleh bupati/walikota dalam bentuk peraturan daerah (Persepsi Undang-Undang Sektoral, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, dll). Jika tidak, maka hak-hak masyarakat hukum adat tidak dapat diperoleh. Persepsi ini tentu saja sangat keliru terutama masyarakat hukum adat yang telah hidup secara turun temurun mengatur, mengelola dan menjaga tanah ulayat yang diatur berdasarkan hukum adat (sifat yang tidak tertulis). Pengaturan tanah ulayat oleh hukum adat pada dasarnya telah diakui oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan-peraturan dasar pokok Agraria (UUPA). UUPA telah mengatur tegas pengaturan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat yakni Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 56 UUPA yang pada pokoknya tanah ulayat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Hakim dan Hukum Adat
Hakim dalam fungsinya pada dasarnya bukan hanya sebagai corong Undang-Undang yang hanya menerapkan aturan hukum tetapi lebih jauh dari itu hakim memiliki tugas mulia yakni menemukan dan menciptakan hukum (Setyanegara, 2013). Penemuan hukum oleh hakim ini telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Makna menggali adalah pada dasarnya hukum sudah ada, tapi masih abstrak, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukum ini harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga apabila telah ketemu hukum, hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusan agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Wantu, 2012). Untuk menemukan hukum adat terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat, hakim harus merujuk pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 56 UUPA. Hakim idealnya mampu menemukan makna tanah ulayat pada konstruksi hukum yang dibangun pada Pasal 3 UUPA yakni menurut kenyataan masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Ketentuan hukum adat yang diatur di dalam Pasal 3 UUPA pada dasarnya sudah sangat jelas namun perlu penemuan hukum oleh hakim untuk menafsirkan syarat-syarat tersebut. Penemuan hukum oleh hakim atas Pasal 3 UUPA menjadi harapan hidup bagi masyarakat hukum adat ketika tanah ulayat yang diperjuangkan oleh masyarakat hukum adat harus berhadapan dengan negara ataupun perusahaan.
Pendekatan hukum dalam melakukan penemuan hukum atas hukum adat tentu tidak serta merta langsung menggunakan pendekatan positivistic, hakim perlu memakai hukum progresif dalam menempatkan hukum pembuktian dalam menemukan penguasaan tanah ulayat. Hal ini menjadi penting olehkarena pendekatan hukum progresif menempatkan hakim untuk rakyat sehingga dalam melakukan penemuan atas Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 56 hakim akan merujuk pada asas-asas hukum adat atas tanah yang secara sosiologis, yuridis dan filosofi ada di masyarakat hukum adat bukan sebaliknya menggunakan hukum barat. Pendekatan hukum progresif dalam penemuan hukum adat dalam perkara tanah ulayat merupakan solusi hakim dalam menangani perkara tanah ulayat. Jika hal ini dilakukan, hakim dalam memutuskan perkara akan dituntun oleh hukum adat untuk menghasilkan putusan yang adil berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
*) Penulis adalah Dosen Hukum Adat
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton