Oleh : Sitti Nurliani Khanazahrah*
Sejak dulu, saya selalu tertarik mengamati bagaimana manusia menjalani hidupnya. Sebagian mereka memilih untuk terus mengejar lebih banyak, sebagian lagi memilih untuk melepaskan. Ada yang mengisi hari-harinya dengan tumpukan ambisi dan kesibukan, lalu ada juga yang perlahan memisahkan diri dari riuhnya dunia, sembari mencari makna dalam kesunyian.
Pernah suatu hari, saya sedang duduk di kantin kampus. Seorang teman yang sudah lama tidak saya jumpai datang menghampiri. Percakapan kami melebar dari kenangan lama hingga ke perbincangan soal hidup yang semakin penuh dengan tuntutan. Ia lalu berkata, “Hidup ini memang lucu ya, semakin banyak yang kita miliki, semakin sering kita merasa kehilangan.”
Pernyataannya membuat saya diam cukup lama. Ada benarnya juga, bahwa semakin kita menumpuk harta, benda, pengalaman, bahkan pencapaian, justru semakin sering kita merasa kosong. Seakan-akan dalam upaya untuk mengisi hidup, kita malah kehilangan esensi dari kehidupan itu sendiri.
Tren minimalisme, yang semakin populer hari ini, bukan sekadar gaya hidup, melainkan sebuah filosofi. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan soal memiliki lebih banyak, tetapi tentang memahami apa yang cukup. Dan sebenarnya, konsep ini bukan hal baru, karena dari zaman kuno hingga sekarang, banyak pemikir besar telah membahas apa pentingnya kesederhanaan.
Di antara mereka, saya tertarik untuk membahas Carl Jung, Arthur Schopenhauer, hingga Rabi’ah al-Adawiyah. Tiga tokoh dengan perspektif yang berbeda, tetapi bertemu dalam satu pemahaman, bahwa kesederhanaan bukanlah keterbatasan, melainkan kebebasan.
Carl Jung, seorang psikolog yang banyak membahas kompleksitas kepribadian manusia, memiliki gagasan yang menarik tentang bagaimana kita membangun identitas. Dalam pandangannya, ada dua aspek utama dalam diri kita, yaitu self (diri sejati) dan persona (topeng sosial).
Persona adalah wajah yang kita tampilkan ke dunia, topeng yang kita kenakan agar diterima oleh lingkungan. Ia adalah ekspektasi, peran, dan citra yang kita bentuk agar sesuai dengan standar sosial. Sedangkan self adalah inti keberadaan kita, diri kita yang autentik, yang tumbuh dari pemahaman mendalam tentang siapa diri kita sebenarnya.
Permasalahan kemudian muncul ketika kita terlalu terikat pada persona. Kita menjalani hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Media sosial turut memperparah situasi ini, karena kita tidak lagi sekadar menikmati hidup, tetapi juga harus memastikan bahwa hidup kita “terlihat menarik.” Kita mesti terus terlihat bahagia, sukses, dan bersemangat, meski sebenarnya lelah dan kosong.
Jung menyebut kondisi ini sebagai keterasingan dari diri sendiri. Semakin kita terjebak dalam persona, semakin jauh kita dari self kita yang sejati. Dan di sinilah sebenarnya, tren minimalisme menemukan relevansinya.
Minimalisme, dalam pandangan Jungian, bukan sekadar bagaimana mengurangi barang atau gaya hidup sederhana. Tetapi, ia adalah proses pelepasan dari persona yang berlebihan. Ini adalah keberanian untuk berkata, “Saya tidak butuh semua ini, saya cukup dengan menjadi diriku sendiri.”
Mereka yang hidup minimalis sering kali bukan hanya membuang barang, tetapi juga membuang beban sosial yang tidak perlu. Mereka tidak lagi merasa harus mengikuti standar kesuksesan yang ditentukan orang lain. Mereka lebih menemukan kepuasan bukan dalam memiliki, tetapi dalam “menjadi.”
Jung mengajarkan bahwa keseimbangan mental tidak terletak pada pencapaian tanpa henti, tetapi pada integrasi antara persona dan self. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan melepaskan segala sesuatu yang tidak esensial, baik itu dalam bentuk harta, status, atau ambisi yang tidak perlu.
Ketika Jung melihat minimalisme sebagai pelepasan dari ilusi persona, Rabi’ah al-Adawiyah, seorang sufi perempuan dari Basra, melihatnya sebagai ekspresi cinta. Baginya, dunia dan segala isinya hanyalah bayangan, sedangkan cinta sejati hanya tertuju pada Tuhan semata.
Rabi’ah menolak segala bentuk kemewahan, bukan karena ia membenci dunia, tetapi karena ia merasa bahwa cinta sejati tidak membutuhkan perantara materi. Ia percaya bahwa hati yang penuh dengan keinginan duniawi tidak akan pernah cukup ruang untuk Tuhan.
Dalam konteks ini, minimalisme bukan hanya tentang mengurangi, tetapi juga tentang menyucikan diri dari ketergantungan pada yang fana. Ini adalah bentuk kebebasan spiritual, di mana seseorang tidak lagi dikendalikan oleh keinginan duniawi. Dalam salah satu doanya yang terkenal, Rabi’ah berkata:
“Tuhanku, jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembah-Mu karena mengharap surga, jauhkanlah aku darinya. Tetapi, jika aku menyembah-Mu karena cinta kepada-Mu, maka janganlah Engkau sembunyikan keindahan-Mu dariku.”
Dari perspektif ini, minimalisme bukan sekadar perihal hidup sederhana, tetapi juga tentang bagaimana kita mengarahkan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Namun, di balik setiap pengejaran, tersembunyi paradoks kepemilikan, apakah kita benar-benar membutuhkan apa yang kita kejar, ataukah kita hanya terjebak dalam ketakutan akan kehilangan sesuatu yang, pada hakikatnya, tak pernah benar-benar menjadi milik kita?
Sementara Jung melihat minimalisme sebagai pembebasan dari persona, dan Rabi’ah melihatnya sebagai ekspresi cinta, Arthur Schopenhauer memandangnya dari sudut yang lebih pesimis, yaitu sebagai jalan untuk melepaskan diri dari penderitaan yang disebabkan oleh keinginan.
Schopenhauer percaya bahwa hidup adalah siklus tanpa akhir dari keinginan dan frustrasi. Kita menginginkan sesuatu, kita mencapainya, tetapi kemudian kita menginginkan lagi sesuatu yang lain. Begitu seterusnya, tidak ada titik akhir dalam siklus ini, kita selalu merasa kurang, dan selalu menginginkan yang lebih.
Ia berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kedamaian adalah dengan mengurangi keinginan itu sendiri. Dalam The World as Will and Representation, ia menulis bahwa manusia akan selalu menderita selama mereka terus mengejar kepuasan yang tidak pernah benar-benar bisa mereka capai.
Minimalisme, dalam pemahaman Schopenhauerian, adalah cara untuk memutus siklus penderitaan ini. Dengan memiliki lebih sedikit keinginan, kita memiliki lebih sedikit kekecewaan. Dengan melepaskan ekspektasi yang berlebihan, kita bisa menemukan kedamaian dalam hal-hal yang sederhana.
Namun demikian, di sini ada perbedaan mendasar antara Schopenhauer dan Rabi’ah. Rabi’ah melihat minimalisme sebagai bentuk cinta yang membebaskan, sementara Schopenhauer melihatnya sebagai cara untuk mengurangi rasa sakit. Meski begitu, keduanya sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepemilikan, tetapi pada pelepasan.
Dari ketiga pemikir ini, kita bisa mengamati bahwa minimalisme bukan hanya tentang mengurangi barang atau hidup lebih sederhana, melainkan ia adalah sebuah kesadaran, sebuah cara untuk melihat dunia dengan lebih jernih.
Jung mengajarkan kita untuk melepaskan persona yang menyesatkan. Rabi’ah mengajarkan kita untuk mencintai dengan murni. Sementara, Schopenhauer mengajarkan kita untuk berhenti mengejar ilusi kebahagiaan yang tak pernah berakhir. Dari ketiganya, saya mengambil benang merah, bahwa dalam kesederhanaan, kita justru menemukan kekayaan yang sesungguhnya.
*) Penulis adalah Staf Pengajar UIN Alauddin Makassar. Aktivitas sehari hari sebagai Pegiat Literasi & Filsafat Profesi. Aktif sebagai Pendiri Rumah Kajian Filsafat dan Pembina Komunitas Literasi Perempuan. Memiliki hoby Baca, Traveling & Menonton.
Email: sittinurlianiindahkhanazahrah@gmail.com.
















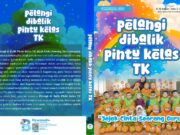























[…] mengeksplorasi Seni dalam Kesunyian, kita pelajari bahwa keheningan bisa sangat menginspirasi. Tokoh seperti Rabi’ah al-Adawiyah […]
Comments are closed.