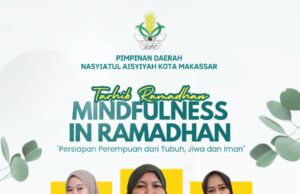Oleh: Fajar Lingga Prasetya.,S.AB
(Analis Kebijakan Ahli Pertama Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara)
Indonesia dikenal sebagai negeri kaya akan sumber daya alam, tempat di mana hutan hujan tropis, tambang mineral, cadangan energi, serta kekayaan laut berlimpah memenuhi hampir setiap jengkal wilayahnya. Dari Sabang hingga Merauke, alam memberi karunia yang tak ternilai. Namun ironisnya, kekayaan luar biasa ini justru menyisakan sebuah paradoks: sumber daya alam yang seharusnya menjadi berkah pembangunan, malah kerap menjadi kutukan karena cara pengelolaan yang serampangan dan eksploitatif. Realitasnya menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia pada ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam telah menimbulkan konsekuensi besar, tidak hanya pada aspek lingkungan tetapi juga ketahanan sosial dan daya saing ekonomi nasional di masa depan.
Selama beberapa dekade, pertumbuhan ekonomi Indonesia dibangun di atas kegiatan mengolah dan menguras kekayaan alam secara langsung. Tambang dibuka, hutan ditebang, lahan pertanian rakyat disulap menjadi perkebunan monokultur raksasa. Sektor ini memang memberikan sumbangan besar bagi perekonomian nasional, data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat lebih dari 30% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih bertumpu pada hasil tambang, perkebunan, dan penggalian sumber daya alam lainnya. Namun di balik angka itu tersimpan harga sosial dan ekologis yang mahal.
Dampak negatif dari menguras alam secara langsung dapat dilihat dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023) mencatat bahwa Indonesia kehilangan rata-rata 650 ribu hektar hutan per tahun dalam dua dekade terakhir, sebagian besar akibat pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan tambang, di Kalimantan terdapat ribuan lubang bekas tambang batubara menganga tak terurus, bahkan ada yang menelan korban jiwa anak-anak yang tenggelam di genangan air bekas galian, tidak hanya mengancam keselamatan warga tapi juga menurunkan kualitas air tanah dan ekosistem sekitarnya. Dari aspek sosial, praktik ekspansi industri ekstraktif sering mengabaikan hak masyarakat adat dan lokal. Di Sulawesi Tenggara, limbah tailing dari pertambangan nikel mencemari pantai dan merusak mata pencaharian nelayan lokal. Kasus Rempang di Kepulauan Riau pada tahun 2023 memicu gelombang protes nasional lewat kampanye #SaveRempang yang menggambarkan konflik agraria akut antara rencana investasi besar dan hak hidup masyarakat adat Melayu yang terancam tergusur. Bahkan yang paling hangat mengguncang Raja Ampat di Papua Barat, saat kabar eksplorasi tambang di kawasan konservasi laut dunia memicu kecaman luas dari publik melalui gerakan #SaveRajaAmpat.
Model ekonomi ekstraktif seperti ini melahirkan ketergantungan struktural. Saat harga batubara dan nikel dunia turun, penerimaan negara goyah. Bahkan 75% produksi nikel Indonesia diekspor ke Tiongkok (Kementerian ESDM, 2022), membuat perekonomian sangat rentan pada fluktuasi permintaan satu negara. Ketergantungan pada komoditas primer menyebabkan perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak harga dunia. Pada 2023 misalnya, penurunan harga batubara global langsung mempengaruhi target penerimaan negara dari sektor minerba yang sebelumnya menyumbang sekitar 10% dari total penerimaan negara. Lebih dari itu, ketergantungan ekspor bahan mentah melemahkan nilai tambah dalam negeri padahal potensi hilirisasi dan industri manufaktur hijau masih terbuka lebar. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa: panas bumi terbesar kedua di dunia, sinar matahari melimpah sepanjang tahun, potensi bioenergi dan angin di pulau-pulau besar. Namun hingga kini, pemanfaatannya baru menyentuh kulitnya saja, yakni kurang dari 10% dari total potensi.
Negara-negara lain sudah membuktikan bahwa transisi hijau bisa membawa kesejahteraan baru. Norwegia mengelola hasil migasnya lewat Sovereign Wealth Fund terbesar di dunia, sambil mengembangkan mobil listrik dan energi terbarukan. Jerman melahirkan ratusan ribu pekerjaan lewat proyek energi angin dan surya. Jerman sukses mengalihkan 45% sumber energi listriknya ke pembangkit terbarukan, menciptakan hampir 300.000 green jobs baru pada sektor ini (IEA, 2022). Bahkan Selandia Baru berani melarang eksplorasi migas baru demi melindungi alam dan masa depan ekonominya. Indonesia pun mulai bergerak. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menetapkan transisi hijau sebagai agenda utama: menurunkan emisi karbon, meningkatkan porsi energi baru terbarukan hingga 23% pada 2025, mengembangkan ekonomi sirkular, hingga menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs).
Namun, jalan ke sana tak akan mudah, diperlukan perubahan paradigma besar dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Transisi ke ekonomi hijau bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Sebab tanpa perubahan arah, Indonesia bisa terjebak dalam lingkaran setan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan stagnasi ekonomi berbasis komoditas mentah. Sebaliknya, bila momentum ini dimanfaatkan, Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi hijau Asia, sekaligus menyelamatkan warisan alam bagi generasi mendatang.
Menghadapi tantangan besar dari warisan ekonomi ekstraktif dan tuntutan global menuju pembangunan berkelanjutan, Indonesia tidak bisa lagi menunda transisi menuju ekonomi hijau. Transisi ini bukan semata demi memenuhi komitmen internasional seperti Paris Agreement atau Sustainable Development Goals (SDGs), tetapi juga demi menjamin ketahanan ekonomi nasional, kualitas lingkungan hidup, dan keadilan sosial bagi generasi sekarang dan masa depan.
Namun transisi ini tidak akan terjadi secara otomatis. Diperlukan intervensi kebijakan yang terarah, konsisten, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan—dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, masyarakat adat, hingga generasi muda. Untuk itu, berikut adalah sejumlah rekomendasi strategis:
- Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA)
Selama ini tata kelola SDA di Indonesia masih sarat dengan kelemahan: tumpang tindih perizinan, lemahnya pengawasan, hingga praktek pembiaran lubang tambang terbuka yang membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Reformasi di sektor ini mutlak diperlukan untuk memutus ketergantungan terhadap eksploitasi SDA mentah. Langkah reformasi ini diantaranya
- Moratorium izin baru untuk tambang dan perkebunan sawit di kawasan hutan primer, gambut, dan wilayah kelola adat.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang meninggalkan kerusakan lingkungan tanpa rehabilitasi.
- Penyusunan peta jalan restorasi lahan rusak, disertai pembiayaan khusus dari Dana Rehabilitasi Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
- Percepatan Transisi Energi Bersih
Sektor energi menyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia. Tanpa pergeseran ke sumber energi terbarukan, target Net Zero Emission tahun 2060 akan sulit dicapai. Selain itu, energi hijau membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk percepatan transisi energi bersih adalah:
- Penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif fiskal bagi investor energi surya, angin, panas bumi, dan biomassa.
- Penetapan target bauran energi baru terbarukan minimal 35% pada 2045, sejalan dengan komitmen NDC Indonesia.
- Penghentian bertahap (phasing out) PLTU batubara lama, diganti dengan pembangkit rendah karbon.
- Hilirisasi dan Pengembangan Industri Hijau
Indonesia tak boleh lagi mengekspor bahan mentah seperti nikel atau bauksit tanpa nilai tambah. Hilirisasi bukan hanya soal peningkatan devisa, tetapi juga memastikan bahwa industri di dalam negeri mengikuti prinsip green industry. Langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk program hilirisasi adalah
Pengembangan kawasan industri hijau, seperti di Kalimantan Utara, berbasis EBT.
Kewajiban proses hilirisasi mineral di dalam negeri, disertai standar ketat pengelolaan limbah industri.
Investasi riset dan pengembangan teknologi energi terbarukan, baterai kendaraan listrik, dan ekonomi sirkular.
- Perlindungan Hak Masyarakat Lokal dan Adat
Transisi ekonomi hijau harus adil. Masyarakat adat dan lokal, yang selama ini paling terdampak proyek ekstraktif, harus menjadi bagian dari solusi, bukan korban baru. Langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya:
- Percepatan pengesahan wilayah adat secara legal melalui Peraturan Daerah (Perda) dan pengakuan hak atas tanah adat.
- Kewajiban pelibatan aktif masyarakat lokal dalam penyusunan Amdal dan izin usaha.
- Program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal: ekowisata, agroforestry, pertanian organik, bioenergi.
- Penguatan Pembiayaan dan Investasi Hijau
Transisi energi dan industri hijau memerlukan sumber pembiayaan besar. Pemerintah harus mendorong lahirnya instrumen investasi hijau serta mendorong sektor perbankan dan keuangan berperan aktif. Langkah-langkah yang dapat diambil adalah:
- Penerbitan green bonds dan sovereign green sukuk lebih masif untuk mendanai proyek hijau.
- Insentif pajak dan pembiayaan murah bagi sektor-sektor ramah lingkungan.
- Kewajiban bagi bank nasional untuk mengalokasikan porsi pembiayaan minimal tertentu untuk proyek berkelanjutan.
- Penguatan Pendidikan, SDM, dan Teknologi Hijau
Ekonomi hijau membutuhkan tenaga kerja baru dengan keterampilan khusus. Tanpa penguatan SDM, Indonesia hanya akan jadi konsumen teknologi hijau dari luar. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:
- Integrasi kurikulum ekonomi hijau di SMK, politeknik, dan perguruan tinggi.
- Pelatihan ulang (reskilling) pekerja sektor lama untuk bisa beradaptasi di industri hijau.
- Dukungan inkubator bisnis dan start-up teknologi lingkungan, khususnya di daerah.
Dengan melaksanakan rekomendasi secara terpadu dan konsisten, Indonesia dapat memutus ketergantungan pada model ekonomi ekstraktif yang telah usang, sekaligus membuka jalan menuju masa depan yang berkelanjutan, adil, dan tangguh secara ekonomi. Transisi ini memang menuntut keberanian politik, sinergi lintas sektor, dan keterlibatan publik luas, namun hasilnya akan sangat menentukan wajah Indonesia pada 50 tahun mendatang