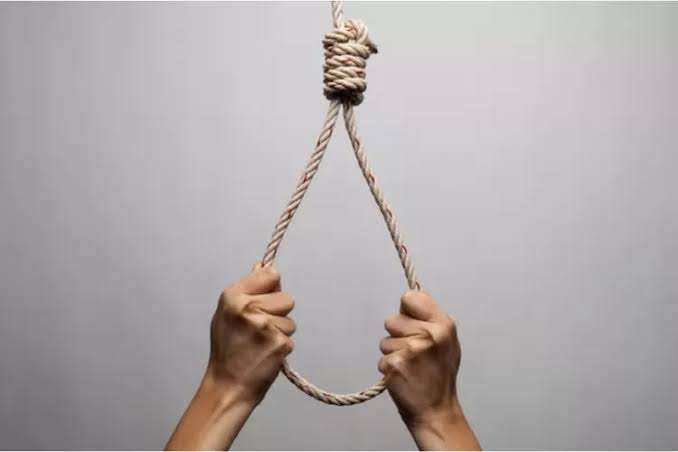Oleh : Sitti Nurliani Khanazahrah*
(Staf Pengajar UIN Alauddin Makassar, Pendiri Rumah Kajian Filsafat dan Pembina Komunitas Literasi Perempuan)
Pagi yang benar-benar sunyi, ketika kabar tentang kematian tak lagi datang dari kecelakaan lalu lintas, antrean rumah sakit atau bencana alam, tetapi dari ruang akademik. Sebuah tempat yang semestinya menjadi lumbung ilmu dan kehidupan.
Beberapa waktu lalu, tepatnya Jumat, 11 Juli 2025, seorang dosen di Universitas Negeri Makassar mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengejutkan. Ia gantung diri, meninggalkan warisan pertanyaan yang menggantung di benak banyak orang. Mengapa seseorang yang tampak begitu terdidik, begitu mapan dalam kariernya, justru memilih untuk pergi secara tragis?
Sebenarnya, fenomena bunuh diri di kalangan akademisi bukanlah hal yang baru, meski sering kita bungkam dalam diam. Di balik toga, artikel jurnal, dan gelar akademik, ada kehidupan manusia yang tak kebal dari sunyi, cemas, dan kelelahan eksistensial. Mereka yang setiap hari membahas teori dan metodologi, ternyata bisa juga kehilangan pegangan untuk menjalani hidupnya sendiri.
Albert Camus (1913-1960), seorang filsuf asal Prancis, pernah menulis bahwa bunuh diri adalah satu-satunya persoalan filsafat yang sungguh-sungguh penting. Baginya, pertanyaan tentang apakah hidup layak dijalani atau tidak adalah akar dari semua pertanyaan lain. Camus menyebut dunia ini sebagai “absurd”, yaitu ketika manusia mencari makna dalam dunia yang tampaknya tak menyediakan jawaban yang pasti. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apakah menyerah adalah satu-satunya pilihan?
Namun Camus tidak berhenti pada absurditas. Ia menawarkan pemberontakan. Bukan pemberontakan fisik, tetapi keberanian untuk tetap hidup dan mencintai hidup, meski tanpa kepastian. Sebuah bentuk keteguhan batin untuk terus berjalan di tengah kekosongan makna. Barangkali inilah yang luput dari banyak orang, bahwa untuk bertahan, kita memang butuh keberanian untuk merangkul absurditas, dan bukan melawannya.
Tetapi keberanian itu tidak tumbuh begitu saja, terutama ketika kita hidup dalam dunia akademik yang semakin menuntut. Dahulu, seorang akademisi cukup dikenal lewat keilmuan dan dedikasinya pada riset dan pengajaran. Kini, muncul tekanan-tekanan baru yang tak kalah berat. Ada tuntutan gaya hidup yang nyaris tak kasatmata namun sangat menekan. Pakaian harus elegan, gadget terbaru harus dimiliki, kendaraan yang dikendarai harus mencerminkan kelas sosial tertentu, dan sebagainya.
Teman saya yang juga seorang dosen muda pernah berseloroh, “Kalau laptopku jadul, mahasiswa tak hormat. Kalau bajuku biasa saja, saya tampak tak berwibawa.” Di balik kelakar itu, saya melihatnya menyimpan kegelisahan. Mungkin memang benar, bahwa kini dunia akademik perlahan bergerak dari ruang pencarian kebenaran menjadi panggung performatif.
Bukan lagi tentang sejauh mana seseorang berpikir, tetapi lebih tentang bagaimana ia tampil. Fashion menjadi simbol status, gadget menjadi lambang prestise, dan kendaraan menjadi penanda gengsi. Tak heran jika banyak akademisi muda terseret dalam pusaran itu, mereka berlomba-lomba menampilkan citra sukses, meski batinnya lelah dan terengah-engah.
Sayangnya, kapasitas akademik, meski tinggi, ternyata tidak selalu sebanding dengan ketangguhan jiwa dalam menghadapi badai kehidupan. Gelar profesor atau doktor tidak serta-merta membuat seseorang imun dari rasa hampa. Bahkan, kadang justru beban keilmuan dan harapan sosial itu membuat seseorang semakin kesepian. Di tengah pencapaian akademik yang diraih dengan susah payah, ada yang lupa membangun ruang batin untuk berteduh.
Pertanyaannya, mungkinkah kita menemukan makna hidup dan kebahagiaan yang sejati di lingkungan kampus? Bisakah kampus menjadi ruang kontemplasi, dan bukan hanya produksi pengetahuan? Dalam sejarah filsafat, banyak yang percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana kita menjalani hidup.
Epikuros (341 SM-270 SM), filsuf dari Yunani Kuno, pernah mengatakan bahwa kebahagiaan terletak pada ketenangan jiwa (ataraxia) dan kebebasan dari rasa sakit (aponia). Ia menolak gagasan bahwa kekayaan dan kemewahan adalah sumber kebahagiaan. Sebaliknya, ia mengajarkan hidup sederhana, bersahabat, dan merenung sebagai jalan menuju kebahagiaan. Dalam konteks kampus, prinsip Epikurean ini mengingatkan kita bahwa hidup akademik tak harus glamor. Kebahagiaan bisa hadir dalam percakapan jujur dengan mahasiswa, dalam tulisan yang lahir dari permenungan, atau dalam waktu-waktu sunyi di perpustakaan.
Perihal bunuh diri, Ibnu Sina (980-1037) dalam kitab Al-Najat, juga menyatakan bahwa jiwa yang sehat adalah jiwa yang mengenali akalnya dan bersatu dengan hakikat wujud. Ia mengisyaratkan bahwa penderitaan jiwa sering kali berasal dari keterasingan manusia dari dirinya sendiri, dari akalnya, dan dari Sang Wujud. Dalam konteks ini, bunuh diri bukan hanya tindakan fisik, tetapi lebih sebagai pertanda bahwa seseorang telah kehilangan orientasi metafisisnya, ia telah lupa untuk mengenali dirinya dalam cermin ruhani.
Di sisi lain, Al-Ghazali (1058-1111) mengingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati hanya ditemukan dalam kedekatan dengan Tuhan. Bukan lewat tumpukan harta, bukan lewat gelar, tetapi lewat penyucian jiwa. Menurutnya, manusia yang hanya sibuk mengejar dunia luar, akan senantiasa merasa kosong karena ia menjauh dari hakikat batinnya. Ini bisa jadi tawaran yang layak direnungkan oleh para akademisi, bahwa kesibukan menulis jurnal dan mengejar hibah tidak akan pernah cukup mengisi relung jiwa jika dilakukan tanpa kesadaran akan tujuan yang lebih tinggi.
Søren Kierkegaard (1813-1855), filsuf eksistensial dari Denmark, juga pernah bicara tentang keputusasaan sebagai penyakit mematikan. Keputusasaan menurutnya adalah kondisi ketika seseorang tidak ingin menjadi dirinya sendiri. Ia tidak damai dengan keberadaannya, dan tidak menerima dirinya sebagaimana ia diciptakan. Dalam dunia akademik, hal ini bisa terlihat pada mereka yang merasa gagal karena tidak mencapai standar yang ditentukan institusi. Padahal, barangkali yang diperlukan adalah keberanian untuk menerima diri dan jalan hidup yang lebih unik.
Bagi saya, semua pemikiran ini mengarahkan kita pada satu titik, bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari pencapaian luar, tetapi lebih sebagai hasil dari pengenalan dan penerimaan diri. Kampus, seharusnya bisa menjadi tempat yang menumbuhkan kesadaran ini. Ia bukan hanya ladang angka kredit, tetapi lebih sebagai taman batin tempat manusia belajar menjadi manusia.
Dalam situasi hari ini, barangkali kita butuh mendefinisikan ulang kebahagiaan. Bukan lagi sebagai akumulasi capaian, tetapi lebih sebagai keintiman dengan diri sendiri. Sebagai keberanian untuk hidup pelan-pelan, untuk berjalan di tengah arus tanpa tenggelam. Sebagai kekuatan untuk tetap mengajar dengan hati, meneliti dengan cinta, dan membimbing dengan empati.
Tulisan ini, tentu saja tak mampu menjawab seluruh pertanyaan tentang bunuh diri. Tetapi minimal, ia bisa menjadi ruang kecil untuk mulai bertanya dengan lebih jujur. Apakah kampus kita masih memberi ruang untuk tumbuhnya jiwa? Apakah kita masih mengizinkan kesedihan hadir, tanpa merasa harus segera menutupinya dengan pencitraan? Apakah kita berani bertanya pada diri sendiri: apa arti hidup yang layak dijalani?
Barangkali jawabannya sederhana. Bukan pada seminar internasional, bukan pada sertifikasi, tetapi pada detik-detik sunyi saat kita berdialog dengan diri sendiri, dan menemukan bahwa kita masih ingin hidup, bukan karena dunia ini sempurna, tetapi lebih karena kita memilih untuk merangkul ketidaksempurnaannya dengan penuh kasih. Dan dari titik itu, mungkin saja hidup kembali punya makna, meski hanya setipis cahaya pagi yang mengintip di sela tirai jendela kampus yang sepi.