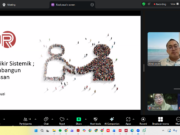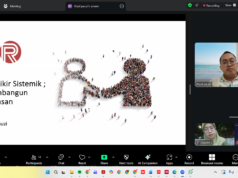Oleh, Fahri Ardiansyah
Literasi, MataKita.co- Francis Fukuyama lewat sebuah tulisannya mengemukakan bahwa ketika abad ke-20 arus wacana ditandai dengan perjuangan ideologis besar antara demokrasi, fasisme dan komunisme maka pada abad ke-21, korupsi menjadi sebuah isu dominan dan menentukan di berbagai aspek kehidupan bernegara. Harus diakui, dalam beberapa tahun terakhir, isu korupsi atau secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi telah menarik perhatian sejumlah akademisi dan praktisi kebijakan. Bukan tanpa alasan, skandal korupsi telah banyak menjerat sejumlah aktor pejabat publik baik di negara-negara industri besar atau negara berkembang dan bahkan berujung pada penggulingan rezim pemerintah berkuasa.
Pada dasarnya ihwal korupsi yang menggejala belakangan ini merupakan fenomena modern. Muncul secara bertahap pada abad 16 dan 17 ketika istilah semacam kontrak sosial telah dipergunakan untuk melindungi kepemilikan publik. Teori-teori seperti Hugo Grotius, Jean Bodin, Thomas Hobbes dan Samuel von Pufendorf perlahan mulai mengemuka, yang secara mendasar mengatakan bahwa seorang penguasa dapat secara sah berdaulat namun bukan dengan hak kepemilikan.
Hal yang tentunya berbeda dengan era di abad pertengahan Eropa, dimana konsep publik dan pribadi belum dikenal luas. Oleh Max Weber diistilahkan sebagai ‘patrimonial’ yaitu ketika otoritas politik dianggap sebagai hak milik pribadi yang dapat diturunkan kepada keturunan sebagai bagian dari warisan mereka. Begitu pula dengan sistem pada zaman dinasti, seorang raja dapat memberikan seluruh wilayah kekuasaanya beserta isinya kepada putra atau putrinya sebagai hadiah, karena ia menganggap wilayahnya sebagai milik pribadi.
Akan tetapi, memasuki era modern dewasa ini, disaat negara-negara terfragmentasi ke dalam bentuk sistem berbeda-beda, berupa perwujudan demokrasi maupun otoriter dan juga pergerakan sistem pasar yang mengalami transisi ke sistem pasar bebas, nampaknya telah memunculkan corak baru perilaku korupsi diberbagai negara termasuk di Indonesia. Kondisi yang terjadi, pejabat publik mencoba melegitimasi demokrasi dan setidaknya berpura-pura mengadakan pemilihan yang kompetitif. Namun kenyataannya, mereka bersembunyi dibalik nilai fantastis biaya politik untuk kontestasi pilkada maupun janji-janji anti korupsi yang kerapkali dijadikan jargon kampanye menjelang pemilihan. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam kurun 2010 sampai 2015 sebanyak 183 Kepala Daerah telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi. Perkara ini semaik menegaskan bahwa penggunaan jabatan politik harus memerlukan pengawasan ekstra guna memutus rantai korupsi yang semakin hari makin mengakar.
Korupsi seolah menjadi siklus panjang yang sulit diputus. Kesenjangan antara political will, penegakan hukum, dan reformasi politik merupakan determinasi utama begitu sulitnya pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh. Sejumlah argumentasi perubahan masih terbatas pada indikator-indikator yang bersifat kontekstual namun terhambat pada tataran implementasi. Para pemimpin politik berpura-pura menjadi pelayan masyarakat dengan ornamen modern seperti parlemen, menteri dan birokrasi. Tapi kenyataannya adalah para elit justru memasuki politik untuk mendapatkan biaya ganti rugi atau sumber daya yang berakhir pada upaya memperkaya diri, keluarga dan kelompok. (Bersambung ke bagian 2)