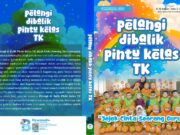Oleh : Muh. Asratillah Senge*
“Orang-orang miskin di jalan,
Yang tinggal di dalam selokan,
Yang kalah dalam pergulatan,
Yang diledek oleh impian,
Janganlah mereka ditinggalkan”
(W.S. Rendra)
Puisi Rendra di atas, walaupun diwartakan beberapa tahun yang silam, tapi tak sulit bagi kita saat ini untuk memverifikasi dan membenarkannya. Kemiskinan, buangan, kekalahan, ledekan dan ketertinggalan adalah hal-hal yang selalu berjalan seiring dengan janji-janji gemerlap dari kota, ibarat sepasang kekasih yang bergandengan tangan di taman.
Di awal kemunculannya, kota lahir dengan niat sebagai pembeda antara ke-adab-an dan ke-biadab-an, antara keterbelakangan dan kemajuan, antara kebodohan dan ketercerahan. Tapi sejarah berkata lain, kota ternyata tidak hanya mempercepat laju kemajuan tapi juga mempercepat kemunculan jenis-jenis keterbelakangan yang tak pernah kita duga sebelumnya. Kota memang telah menjadi pusat keberadaan universitas-universitas di mana kita dapat dengan mudah melihat orang-orang yang menenteng buku ke sana kemari, tapi kita juga bisa melihat begitu banalnya kebodohan di sudut-sudut kota (kekerasan, intoleransi, pelecehan seksual dll.)
Di Eropa selama berjalannya deru Revolusi Industri, kota telah dijadikan sebagai pusat untuk melakukan rekayasa politik, sosial dan ekonomi. Yah kata kunci di sini adalah “rekayasa”, dan dalam kata “rekayasa” terselip mantra “penaklukan”, pertanyaannya apa yang hendak ditaklukkan oleh kota ?, jawabnya adalah “rasa takut akan ketidakpastian”. Kota-kota di bangun untuk menaklukkan bentang alam rawa, hutan liar, padang pasir, sabana ( dan mungkin ke depan “samudera” dan “ruang angkasa” akan ditaklukkan pula oleh kota-kota) yang terpapar luas dan tak berbatas, maka dari itu rentan akan ketidakpastian cuaca, mata pencaharian, pangan dan tentunya nasib.
Hari Juliawan mengatakan, cetak biru pembangunan kota di Indonesia mengikuti mantra yang sama, yakni mantra “penaklukan”. Kita ambil contoh saja, serangkaian kebijakan di era Orde Baru, yang telah merubah tekstur ekonomi kita secara mendasar. Pada tahun 1980 sektor pertanian menyumbang 24 persen dari PDB Indonesia, lalu turun terus menerus pada tahun-tahun berikutnya. Hingga pada tahun 1997 industri manufaktur menyumbang 51 persen terhadap produk ekspor, yang pada tahun 1980 yang menyumbang 2 persen.
Meningkatnya produktivitas sektor industri ini, memberi daya tarik sendiri bagi kota-kota besar di Indonesia. Tenaga kerja dari pedesaan hijrah besar-besaran ke perkotaan, mungkin karena mereka melihat kota sebagai tempat berkumpulnya jenis-jenis pekerjaan formal yang dianggap mewakili kondisi kerja modern. Kota semacam lentera kemajuan bagi ngengat-ngengat yang berbondong-bondong. Mereka tertarik akan pekerjaan yang menyediakan semacam jenjang karir, kondisi kerja yang layak, jaminan kesehatan dan pensiun. Kota menjadi wadah yang begitu gemerlap ataupun ruang pemenuhan hasrat untuk menjadi modern dan terjauhkan dari keterbelakangan.
Lalu tibalah krisis ekonomi di tahun 1997-1998, gemerlapnya kota tiba-tiba menjadi suram. Kota-kota besar di Indonesia, berubah dari wadah bagi harapan-harapan, menjadi wadah kecemasan-kecemasan dan keputusasaan. Maka meletuplah penjarahan-penjarahan, kekerasan-kekerasan, keluhan-keluhan dan segala bentuk kebodohan. Walaupun setelah masa krisis kota-kota kembali menggenjot pertumbuhan ekonomi, tapi ada kecenderungan pertumbuhan tidak berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja, pemerataan dan mungkin kebahagiaan. Kota telah menjadi semacam “makhlukh paradoks”, di satu sisi dia menjanjikan bahwa mimpi bisa didongkrak menjadi kenyataan, di satu sisi kota bisa menjadi semacam “crusher machine” yang meremukkan dan menghancurkan mimpi sampai menjadi remah-remah yang tak bisa lagi dikatakan sebagai “mimpi”.
Menurut Nirwono Joga dkk. Kota-kota kita saat ini tengah menghadapi 6 persoalan. Pertama, pertumbuhan penduduk di kota-kota Indonesia melaju dengan pesat, dalam empat dekade terakhir (1970-2010) telah meningkat enam kali, dari 14,8 persen (1961), 17,4 persen (1971), 23 persen (1980), 30,9 persen (1990), 42,43 persen (2000), 49,79 persen (2010). Dan diperkirana populasi penduduk perkotaan akan bertambah menjadi 80 % di tahun 2050. Data ini menunjukkan beban kota akan semakin besar dari tahun ke tahun, akan semakin banyak orang yang menggantungkan nasib mimpinya pada kota.
Kedua, Soal peluberan kota terjadi hingga ke pinggiran kota sekitarnya. Sebaran kawasan yang terbangun telah menjalar dari kota inti dan bergantung pada infrastuktur yang dibangun oleh pemerintah. Ketiga, soal kualitas lingkungan perkotaan, mulai dari soal kenaikan permukaan air laut 0,73-0,76 sentimeter pertahun, penurunan muka tanah 4-20 sentimeter per tahun (akibat penggunaan air tanah yang tak terkendali) hingga ke peningkatan gas rumah kaca hingga 75 persen.
Keempat. 86 persen dari kota-kota Indonesia kita telah memiliki, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tapi hanya 20 persen dari RTRW kota yang memasukkan perubahan iklim sebagai salah satu agendanya. Padahal perubahan iklim selain sebagai hal yang natural juga merupakan resultan dari dari respon kultural kita terhadap lingkungan hidup. Kelima, harus diakui bahwa kota telah memberikan sumbangan sebesar 74 persen terhadap PDRB nasional. Tapi pembangunan infrastruktur yang berfokus pada perkotaan, mengakibatkan bertambah besrnya jurang kesenjangan antara kota dan desa semakin besar. Keenam, pembagunan kota yang cenderung berpihak pada modal telah membuat 6,96 persen penduduk kota tinggal di kawasan kumuh, 7,6 juta backlog perumahan dan baru mampu mencakup 56 persen layanan pengelolaan sampah.
Kota-kota kita membutuhkan lebih banyak asupan tenaga baru, berupa gagasan-gagasan progresif mengenai perubahan yang inklusif dan berkeadilan. “Orang-orang kalah” di perkotaan hendaklah menjadi pertimbangan utama, bukan hanya sebagai sasaran derma dan budi baik, mereka harus terlibat dalam merangkai ulang cita-cita kota. Karena di dalamnya mereka turut “hidup” bersama kita.
Lalu bagaimana dengan Kota Makassar ?, apakah kita berbangga dengannya hanya karena semakin bisingnya deru kendaraan di jalan raya ? Lalu apalah arti pilar-pilar beton berdiri kokoh di sana-sini, tapi pemerataan ekonomi tak kunjung terwujud ? Apalah arti festival-festival, jika nilai-nilai budaya lokal justru semakin layu ? Apalah arti slogan-slogan berhamburan, jika perilaku korup tetap subur di birokrasi?
*) Penulis adalah Direktur Profetik Institute