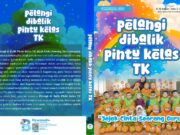Oleh : Wahyudi Akmaliah*
Sebagai sarjana pemula, saya perlu mengajukan pertanyaan ini. Selain sebagai bentuk advokasi juga untuk melakukan semacam refleksi mengapa sarjana Indonesia banyak menulis di jurnal-jurnal predator. Pertanyaan mengapa sarjana Indonesia banyak menulis di Jurnal predator ini yang perlu direfleksikan lebih jauh, bukan justru menyalahkan. Ini karena kehadiran Jurnal predator itu tidak akan tumbuh massif jika tidak ada konsumennya. Konsumen tentu saja tidak ada kalau engga ada aturan main yang membuat orang tergerak untuk menulis di jurnal indeks-indeksan.
Di sisi lain, dunia akademik kita sebenarnya belum tumbuh untuk memperkuat basis riset dan iklim kesarjanaan. Sebaliknya, struktur birokrasi kemudian menjadi pengganjal utama sekaligus jalan pintas di tengah orang kesulitan untuk menulis di Jurnal internasional sebagai syarat kenaikan pangkat. Harus diakui, tidak banyak juga, sarjana Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri, membuatnya untuk belajar menulis akademik di jantung peradaban barat.
Akibatnya, menulis di Jurnal internasional adalah jalan yang sangat berdarah-darah. Memang harus diakui, kebanyakan Jurnal bereputasi internasional tidak mengeluarkan uang bagi sarjana yang ingin menerbitkan karyanya. Namun, apabila tulisannya ingin dianggap pantas harus melalui proofread dengan ahli atau native speaker yang tidak murah. Ini sangat berat, melampaui cicilan perbulan saya kpr!. Meskipun sudah dilakukan proofread belum tentu karya kita bisa dimuat. Bahkan, ketika ingin dimuat pun bisa saja batal karena satu dan lain alasan.
Di sini, saya ingin menegaskan bahwa iklim akademik kita belum tumbuh ke arah sana, tapi tiba-tiba dipaksa dengan iming-iming uang dan syarat kenaikan pangkat. Tidak sedikit yang menempuh jalur berdarah-darah, termasuk saya, sementara itu, ada banyak yang kemudian menempuh jalan pintas. Menyalahkan mereka yang menulis di Jurnal predator sebenarnya bentuk cermin akademik kita sendiri yang tidak membangun budaya akademik sejak dini.
Selain itu, khusus ilmu sosial dan humaniora, produksi pengetahuan kita sudah lama dibentuk oleh sarjana Amerika, Eropa, dan Australia. Kalau mau masuk dalam liga Jurnal internasional bertanding dengan mereka, selain harus membaca karya-karya mereka, tapi kita harus mengkritik mereka. Nah, di sini persoalannya, kita tidak memiliki semacam otonomi ilmu sosial sebagai alat untuk mengkritik. Yang muncul kemudian adalah bentuk ritus pujian dari karya-karya mereka yang sangat eropa dan Amerika sentris dalam membaca Indonesia.
Saran saya, berhenti menyalahkan mereka yang sudah mau berusaha keras, meskipun akhirnya terjerembat dalam Jurnal predator. Selain itu, kita harus melakukan otokritik dengan membongkar ulang kurikulum pendidikan tinggi yang menghargai proses kerja keras dan apresiasi. Tentu saja, kita sambil terus mengingat bahwasanya candi Borobudur itu tidak dibangun dalam waktu semalam, melainkan puluhan tahun dengan kerja-kerja detail, penuh pengorbanan, sekaligus juga rasa estetis tinggi.
*) Penulis adalah Peneliti LIPI