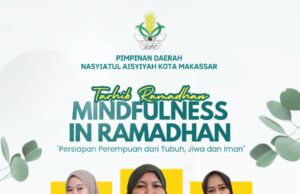Oleh : Idham Malik*
Trend pembelian udang terlihat membaik dari tahun ke tahun (meski realitas di lapangan, pada musim corona ini harga udang agak berkurang), misalnya tahun 2015 hanya sekitar 1.863.135 ton, pada 2018 sudah menjadi 2.222.882 ton, bahkan di masa-masa corona tahun 2020, pasar udang global tembus 2.749.558 ton. Dari paparan Tinggal Hermawan, SPi, MSi, dalam presentasinya tentang Kebijakan KKP terkait Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem, ternyata pasar Cina yang menyebabkan permintaan itu melonjak. Bayangkan, trend peningkatan pasar udang Cina sebesar 68,78%, sedangkan Amerika Serikat hanya 5,11%. Cina pun menempati urutan pertama trend peningkatan nilai pasar global yaitu sebesar 55,61%.
Barangkali, gara-gara permintaan Cina akan udang yang tinggi ini, mendorong KKP untuk menetapkan target yang cukup ambisius, yaitu peningkatan produksi udang sebesar 250 persen di tahun 2024, yaitu sekitar 1.290.000 ton, jika dibandingkan angka produksi tahun 2019 sebesar 517.397 ton.
Target yang tinggi itu membuat pejabat KKP memutar otak. Apalagi menyaksikan kenyataan di lapangan yang menunjukkan kondisi sebaliknya, seperti data DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Sulsel, pada 2018 berkisar 46.524 ton menurun sekitar 4% pada 2019 menjadi 44.520,5 ton. Apalagi komoditas udang windu, menurun dari tahun ke tahun, tahun 2014: 16.036 ton, tahun 2015: 14.835 ton, tahun 2016: 14.776 ton, tahun 2017: 12.045 ton, dan tahun 2018 hanya 10.169,5 ton. Penurunan windu ini karena begitu massifnya peralihan budidaya dari windu ke vannamei.
Gelora menuju industrialisasi perikanan yang diimpikan oleh pemerintah ini pun mendorong banyak pihak untuk berfikir. Hal ini terekam saat pertemuan Rakor Pengembangan Kluster Udang Nasional pada 13-15 Oktober 2020. Salah satunya yaitu tenaga ahli Kemenkomarves, yaitu Hasanuddin Atjo.
Dr. Hasanuddin Atjo mencontohkan studi kasus Sulawesi Selatan, menurutnya terlebih dahulu mesti ada klaster potensi budidaya, dimana bagian selatan Sulsel menurut Atjo potensial untuk dikembangkan menjadi kluster industrialisasi udang. Daerah selatan yang dimaksud yaitu Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Bulukumba. Pada kluster selatan itu, saat ini, dengan luas area 10.791 ha dapat menghasilkan 5.926,1 ton, sedangkan kluster timur yang luasnya 51.727 ha hanya dapat menghasilkan 5.862,9 ton.
Hasanuddin Atjo juga mengakui banyak tantangan menuju industrialisasi ini, meski masih memungkinan. Diantara faktor kritis menurut Hasanuddin Atjo, yaitu tunjangan lingkungan, kelembagaan, penyakit udang, infrastruktur, rantai dingin, serta nilai tambah. Ia pun mengusulkan untuk disusun terlebih dahulu roadmap industrialisasi udang Sulsel serta masterplan dan rencana aksi kluster.
Sedangkan Dr. Iqbal Djawad yang merupakan tenaga ahli untuk pengembangan udang windu melihat persoalan ada di induk udang, kualitas air, manajemen sumberdaya manusia dan pasar. Salah satu strategi menarik yang diusulkan oleh Iqbal, yaitu menjadikan udang windu sebagai branded food, dengan penguatan promosi dan perluasan pasar ekspor, serta penguatan sdm melalui memasukkan kurikulum tambak ke pendidikan level SMP-SMA serta pelatihan secara annual kepada para pembudidaya udang.
Namun, tampaknya ini masih sulit, mengingat kondisi petambak kita yang masih 94-95 persen adalah petambak skala kecil, dengan segala ikutannya, seperti modal, keterampilan/skill, mentalitas, kebiasaan, akses informasi, akses pasar, akses modal, dan masih terdapat ketergantungan pada bantuan pemerintah.
Pemaparan Direktorat Kawasan dan Kesehatan ikan menunjukkan hal itu, bahwa tambak nasional seluas 804.017,87 ha didominasi oleh tambak sistim sederhana (93% tambak tidak gunakan kincir) di 33 Provinsi, 162 Kab/kota dan 753 Kecamatan. Misalnya di Pinrang (kantung udang Sulsel), budidaya udang dengan tanpa kincir sekitar 12.273,29 Ha atau 99,92% dan budidaya dengan kincir 9,67 Ha atau hanya 0,08%. Jika mengacu pada data DKP Sulsel, Rumah Tangga Perikanan (RTP) di Pinrang untuk tambak skala kecil/tradisional yaitu 9.369 RTP, sedangkan untuk tambak semi intensif sebanyak 10 RTP, dan tambak supraintensif hanya ada 3 RTP.
Bisa dibayangkan strategi seperti apakah yang akan ditempuh oleh pengambil kebijakan untuk mendongkrak produksi, misalnya di Sulsel, dari dari 31.985,5 ton pada 2019 menjadi 79.963,75 ton pada 2024?
Jika meminta para petambak skala kecil/tradisional itu untuk memaksakan diri melakukan perbaikan produksi dalam rentang waktu 5 tahun, dengan berbagai kendala infrastruktur, kualitas lingkungan, kualitas benur, kelembagaan, struktur sosial dan struktur kepemilikan lahan tambak, yang masih banyak di antara mereka adalah penyewa lahan, juga banyak di antara mereka belum konsentrasi dalam memelihara udang, karena beratnya tuntutan hidup, sehingga mesti melakoni beberapa pekerjaan, misalnya petambak sekaligus petani, sekaligus peternak, dan mungkin sekaligus nelayan.
Lantas, apa yang membuat pemerintah terlihat begitu optimis? Pada Agustus 2021 lalu dari beberapa media online telah terdapat kesepakatan antara DJPB (Direktorat Jendral Perikanan Budidaya) yang diwakili oleh TB Haeru Rahayu dengan Arif Sugianto, Bupati Kebumen Jawa Tengah, dan disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Apa yang disepakati? yaitu penerapan Shrimp Estate di Kebumen. Shrimp Estate ini berupa pengelolaan lahan minimal 1000 ha untuk dijadikan kawasan budidaya dengan penerapan tambak udang terintegrasi hulu hilir. Penerapan Shrimp Estate ini dianggap dapat mendorong target 2 juta ton/tahun, dengan mengsyaratkan kegiatan produksi dilakukan dengan biaya yang rendah, menghasilkan produk yang berkualitas, terhindar dari penyakit, berproduksi secara berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Pada shrimp estate ini akan disediakan pembenihan (hatchery), pabrik pakan, lahan budidaya (on farm), Instalasi pengolahan limbah, prosessing dan cold storage, pabrik es, dan laboratorium. Strategi ini diasumsikan akan menyerap banyak tenaga kerja, termasuk tenaga kerja professional. Satu kluster shrimp estate saja diestimasikan dapat menyerap 3.233 orang dengan total gaji keseluruhan yaitu Rp. 15.878.500.000. Tapi, yang menjadi pertanyaan lanjut, seperti apa pengelolaan lingkungannya?
Heran saja, karena dalam presentasi itu disebutkan bahwa penerapan shrimp estate ramah lingkungan dan penyakit dapat dikendalikan, yang kemudian dikontraskan dengan praktik budidaya tradisional yang dianggap tidak ramah lingkungan dan penyakit tidak terkendali. Cerita iklan ini sedikit mirip dengan iklan pembasmi nyamuk, yang diklaim tidak berdampak pada kesehatan orang yang menghirupnya.
Sebab, pada beberapa kasus yang ditemui di lapangan, justru tambak intensif dan supraintensif inilah yang menjadi punya dampak lingkungan, berupa potensi sedimentasi, kekeruhan air, sumber penyakit/patogen/bakteri, serta di beberapa tempat untuk pembuatan tambak padat modal ini didahului dengan penebangan/konversi ekosistem mangrove.
Kehadiran IPAL (instalasi pengolah air limbah) belum menjadi jaminan air yang dibuang ke laut bebas dari limbah. Apalagi, konteks saat ini, masih kurangnya pengawasan terhadap pembuangan limbah oleh tambak tambak intensif maupun supraintensif.
Meski begitu, kita mesti percaya pada pimpinan, Shrimp Estate ini mungkin saja ramah lingkungan, sebab di bagian luar kawasan tambak akan dilakukan penanaman mangrove.. hufff.. Kasihan juga mangrovenya, akan memperoleh beban penanggulangan limbah dari tambak intensif/supraintensif.
Pertanyaan berikutnya yang sedikit mengganggu, yaitu siapa yang diuntungkan dalam bisnis ini? Apakah terdapat petambak tradisional yang lebih dari 90% itu? Dari presentasi Pak Tinggal Hermawan, mula-mula dengan merubah sebagian tambak tradisional menjadi tambak shrimp estate, namun apabila tidak memungkinkan akan menggunakan lahan baru milik masyarakat. Menurutnya, dibutuhkan sekitar 11.000 ha lahan untuk shrimp estate, dimana sekitar 45%-nya atau 5000 ha akan dibangun oleh pemerintah, sedangkan sisanya didorong ke pihak swasta. Lantas, jika pemerintah dari mana sumber keuangannya? dalam presentasi tercatat sumber dana dari non APBN dan melalui Pinjaman dalam dan luar negeri. Hem.. mudah-mudahan program ini berhasil dan kembali modal, karena salah satu skenario pemerintah dalam bentuk pinjaman dana dari luar.
Untuk lebih mendukung pihak swasta ataupun investor, pemerintah akan melakukan simplifikasi perizinan pertambakan, dari 21 perizinan akan hanya menjadi 3 izin dengan sistem 1 pintu. Perizinan yang diminta hanya NIB (BKPM), Izin Lingkungan (KLHK) dan SIUP (KKP). Tidak perlu lagi izin peruntukan penggunaan tanah, CBIB/Indogap, izin pengelolaan air laut selain energi, izin pengelolaan pemasangan pipa dan kabel bawah laut, izin penampungan limbah B3, Izin pembuangan air limbah cair, izin pengambilan air tanah, izin penampungan BBM dll. Bahkan, kepolisian negara republik Indonesia sudah mengeluarkan surat edaran moratorium penindakan terkait perizinan usaha tambak udang. Dengan begitu, jika dan sepertinya sulit petambak tradisional untuk didorong untuk peningkatan produksi, mau tak mau pemerintah akan dan mungkin sedang melirik pemodal besar dalam dan luar negeri untuk mengisi ceruk itu. Sehingga, siapa yang diuntungkan dari program ini? Ya.. lagi-lagi adalah pemilik modal itu sendiri.
Lantas, bagaimana nasib 94-95% petambak tradisional ini? Saya kira untuk kelompok masyarakat ini pemerintah masih punya jurus lain, seperti Kampung Budidaya dan penerapan EAA (Ecosistem Approach to Aquaculture)/ADPE (Akuakultur Dengan Pendekatan Ekosistem), yang sedikit condong ke petambak tradisional. Meski begitu, jika energi pemerintah terbagi untuk pengembangan tambak intensif pada daerah-daerah baru, tidak menutup kemungkinan para petambak tradisional ini akan kembali ke rutinitas biasa, menjalani kebiasaan bertambak seperti yang lalu-lalu.
Hingga akhir tulisan ini, saya masih termangu-mangu, membayangkan target peningkatan 250% produksi udang dalam rentang 5 tahun, dengan kondisi petambak kita yang 95% tradisional. Apakah ini seperti mimpi Lompatan Jauh Ke depannya Mao Zadong? Namun, apa mau dikata ini sudah jadi program dan strategi pemerintah, kita mau bagaimana lagi? Mau windu, ah sudahlah.
*) Penulis adalah penggiat Aquaculture Celebes Community dan koordinator Kader Hijau Muhammadiyah Sulsel