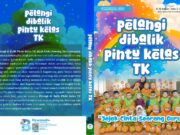Oleh: Rian Suheri Akbar, S. H.
(Pembimbing Kemasyarakatan/PK Ahli Pertama Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan UPT. Bapas Kelas II Palopo)
Di tengah masyarakat, kata “penjara” masih sering digunakan secara bebas untuk menyebut tempat seseorang menjalani hukuman pidana. Tak sedikit pula pemberitaan media yang menggunakan istilah ini tanpa mempertimbangkan konteks atau perkembangan hukum. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia yang modern dan beradab, istilah “penjara” sejatinya telah ditinggalkan dan digantikan dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Perubahan ini bukan sekadar kosmetik bahasa. Ia mencerminkan filosofi baru dalam memperlakukan narapidana — dari sekadar objek hukuman menjadi subjek pembinaan. Maka penting untuk kita sadari: Lapas bukanlah “penjara” dalam pengertian lama yang sarat dengan stigma dan pembalasan.
Dari Balas Dendam ke Rehabilitasi
Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, paradigma hukum pidana di Indonesia secara resmi berubah. Fokus pemidanaan tidak lagi hanya pada pemberian efek jera, tetapi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:
> “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk narapidana agar menjadi manusia yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.”
Dengan kata lain, narapidana bukan lagi dipandang sebagai musuh masyarakat yang harus disingkirkan, melainkan sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi.
Mengapa Istilah “Penjara” Perlu Ditanggalkan?
Istilah “penjara” berasal dari sistem kolonial Belanda yang represif. Dalam sejarahnya, penjara adalah alat kekuasaan untuk menghukum, mengasingkan, dan menundukkan rakyat jajahan. Tidak heran jika kata ini sarat dengan kesan kelam: tempat siksaan, kekerasan, dan tanpa harapan.
Sebaliknya, konsep Lapas mengedepankan pembinaan, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pendekatan psikososial. Narapidana dibimbing untuk mengenali kesalahan, mengembangkan potensi, dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat.
Seperti dikatakan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Reynhard Silitonga:
> “Kami ingin masyarakat melihat Lapas bukan sebagai tempat hukuman semata, tapi tempat pembinaan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.”
Tantangan di Lapangan
Tentu, kenyataan di lapangan masih jauh dari ideal. Overcrowding, kekurangan SDM, dan fasilitas yang terbatas masih menjadi tantangan besar. Namun, menyebut Lapas sebagai “penjara” justru memperpanjang stigma dan menghambat proses perubahan itu sendiri.
Sebagaimana dikatakan Nelson Mandela yang pernah menjalani masa panjang di balik jeruji:
> “It is said that no one truly knows a nation until one has been inside its jails. A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones.”
Mengubah Cara Pandang
Mengganti istilah “penjara” menjadi “Lapas” bukan hanya perkara semantik, tapi juga soal mengubah cara pandang kita terhadap keadilan. Ini adalah bagian dari revolusi mental dalam menegakkan hukum yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.
Kita tidak sedang menghapus hukuman, tetapi menyempurnakan tujuannya. Jika masyarakat terus-menerus memakai istilah “penjara” dengan konotasi lama, maka proses pembaruan sistem pemasyarakatan akan berjalan pincang — karena pembinaan tanpa kepercayaan publik akan selalu kehilangan arah.
Penutup
Lapas bukan tempat untuk membuang manusia. Ia adalah ruang transisi untuk memperbaiki, membentuk ulang, dan mengembalikan manusia ke tempatnya di tengah masyarakat. Maka, sudah waktunya kita, sebagai masyarakat, ikut mengubah pola pikir dan bahasa kita.
Karena dengan menyebut Lapas sebagai “penjara,” secara tidak sadar kita juga menolak harapan, menolak perubahan, dan menolak kemanusiaan.