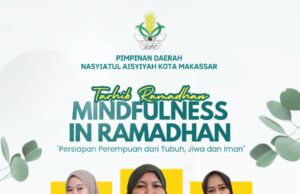Oleh : Muh. Asratillah Senge*
Demokrasi adalah sesuatu yang meriah, di mana segala level kekuasaan atau kepemimpinan dikontestasikan, mulai dari tingkat RW, Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga kursi Presiden. Bukan hanya meriah, tetapi juga mampu menggerakkan harapan-harapan para warga, mampu memobilisasi kepentingan-kepentingan yang semuanya kemudian memadat dalam satu kata yaitu “suara”. Tapi di tengah-tengah kemeriahan demokrasi, yang ada bukan sekedar harapan dan kepentingan, tak jarang kekecewaan-kekecewaan juga terselip bahkan membuncah di dalamnya.
Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menakar sejauh mana warga menaruh harapan pada demokrasi adalah tingkat partisipasi politik. Tingkat partisipasi politik yang sering kita maksud adalah tingkat partisipasi dalam prosedur-prosedur demokrasi terutama dalam momen-momen Pilkada, Pileg dan Pilpres, dengan kata lain “partisipasi politik” seringkali kita sederhanakan menjadi “partisipasi pemilih”. Partisipasi pemilih kini menjadi takaran kita untuk mengukur tingkat legitimasi prosedur kekuasaan yang sah, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih maka semakin legitimate kekuasaan tersebut dan begitu pula sebaliknya.
Barusan saja negara kita, melakukan hajatan politik yang cukup meriah yakni pilkada di beberapa daerah secara serentak, tetapi walaupun meriah, itu tak berarti tingkat “partisipasi pemilih” seratus persen. Jika kita merujuk ke beberapa Pilgub yang lalu, maka ada saja warga yang tak “memilih”, di Jawa Barat ada sekitar 27 persen dari seluruh wajib pilih, di Jawa tengah ada sekitar 37 persen, Jawa timur sekitar 37 persen, Sumuatera Utara sekitar 31 persen dan Sulawesi Selatan sekitar 26 persen. Walaupun jumlah yang “golput” ini tak sebesar dibanding pilkada-pilkada yang lalu, tapi ini tetap masih menjadi pertanyaan, mengapa ada-ada saja yang tak menggunakan hak pilihnya ?.
Banyak jawaban terhadap pertanyaan tersebut, kalau misalnya kita merujuk ke argumentasi Ned Augenblick & Scott Nicholson dalam Ballot Position , Choice Fagitue and Voter Behavior, maka golput bisa saja disebabkan oleh “keberlimpahan” informasi tentang pilihan kandidat. Keberlimpahan yang dimaksud di sini bukan sekedar bahwa secara kuantitatif para kandidat banyak menginformasikan mengenai profil dirinya ke publik, tetapi yang jadi soal justru banyaknya informasi yang simpang siur soal kandidat. Contoh yang paling lucu bagi saya adalah, simpang siurnya beberapa publikasi hasil survey mengenai tingkat keterpilihan kandidat pilkada, beberapa lembaga survey mempublikasi hasil survey yang berbeda bahkan jauh berbeda. Belum lagi hoax yang disebar via medsos, yang makin memperparah kesimpang siuran informasi.
Jika kita menerapkan “logika pasar” dalam kontestasi demokrasi, maka harus diasumsikan bahwa para pemilih nanti sempurna dalam menentukan pilihan jika dan hanya jika memiliki informasi yang sempurna pula tentang yang akan dipilih. Tapi dalam dunia ril, informasi tidak akan mudah terdistribusi secara mudah, dan tidak akan mudah diakses secara sempurna, sering terjadi ketimpangan akses terhadap informasi. Belum lagi pemilintiran informasi (information spin) adalah sesuatu yang jadi lumrah dan massif saat ini.
Jawaban lain tentang penyebab golput, ada persepsi bahwa pilkada adalah momen yang berkait erat dengan kepentingan elit semata, dan tidak ada sangkut pautnya denan kepentingan rakyat di akar rumput. Rakyat di akar rumput tidak merasakan koresponedensi langsung antara “memberikan suara” dengan “terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan politik” mereka, prosedur demokrasi seakan-akan tak tertanam lagi (dis-embedded) di lahannya yang sebenarnya yaitu kepentingan rakyat banyak. Salah satu yang memperkuat persepsi tersebut, adalah fenomena pemberian rekomendasi parpol ke kandidat-kandidat kepala daerah, yang seringkali tidak sejalan dengan mayoritas kader-kadernya sendiri apalagi konstituennya. Belum lagi tidak optimalnya praktik otonomi daerah ditambah banyaknya kepala daerah, terutama di 22 provinsi yang terkena OTT KPK, semua hal ini mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada elit politik sekaligus mencurigai bahwa momen-momen pilkada hanyalah untuk kepentingan elit semata.
Tapi yang harus diingat bahwa tingkat “partisipasi pemilih” belum sepenuhnya menggambarkan “partisipasi politik” warga negara, karena “partisipasi politik” memiliki denotasi (konteks) yang lebih luas, bukan hanya berkaitan dengan pemberian suara di bilik suara, tetapi juga berkaitan erat dengan sejauh mana warga negara mampu mengakses, terlibat dan mempengaruhi segala bentuk kebijakan yang dihasilkan para pemangku kebijakan. Karena ada beberapa pihak yang menjadi golput justru dikarenakan cukup intensnya dalam mengakses informasi politik, tetapi karena beberapa fenomena politik dianggap tidak sesuai dengan kerangka nilai yang dimilikinya, maka sampai pada kesimpulan bahwa sistem atau proses politik yang ada tak layak dilegitimasi melalui “pemberian suara”.
Jika kita mengikuti argumentasi Morris Rosenberg, maka ada tiga alasan seseorang mau berpasrtisipasi atau melakukan aktivitas politik. Pertama, jika keterlibatan dalam aktivitas politik tidak dianggap sebagai ancaman, apakah ancaman terhadap usaha bisnis yang dimiliki, ancaman terhadap karir bahkan ancaman terhadap jiwa dan keluarga. Pasca 1998 keterlibatan politik yang mengancam jiwa, keluarga, usaha bisnis atau karir mungkin akan jarang dijumpai. Yang mungkin ada adalah pembatasan aktivitas (pilihan) politik, maksudnya warga negara secara individu dalam menentukan pilihannya sangat sulit steril dari desakan-desakan eksternal, apakah itu desakan dari keluarga besar, pimpinan di tempat kerja, tokoh masyarakat yang ada, pimpinan parpol, tokoh agama dll. Prinsip “one man one vote” secara prosedural mungkin saja, tetapi secara substansial adalah sesuatu yang sulit.
Kedua. Jika keterlibatan dalam aktivitas politik membawa sesuatu yang bermanfaat. Istilah “manfaat” di sini masih bisa ditafsirkan secara beragam. Apakah manfaat yang dimaksud sekedar manfaat jangka pendek atau manfaat jangka panjang. Ketiga, Jika keterlibatan dalam aktivitas politik dianggap dapat memenuhi kebutuhan material maupun immaterial. Dalam perspektif pertukaran, aktor politik merupakan makhlukh yang rasional yang mempertimbangkan untung-rugi jika melakukan transaksi politik. Keuntungan yang diperoleh dalam transaksi tersebut bisa saja transaksi yang bersifat intrisik semisal perhatian, pengayoman, dukungan maupun dorongan, ataukan keuntungan yang sifatnya ekstrinsik semisal uang, sembako, posisi , jabatan dll.
Dan akhirnya, demokrasi kapanpun dan di mana pun, berkepentingan akan tingkat “partisipasi politik” yang intens dari warganya, karena sumber legitimasi dan denyut nadi kehidupan demokrasi berasal dari “partisipasi” warga negara.
*) Penulis adalah Direktur Profetik Institute dan wakil ketua Partai Perindo Sulsel