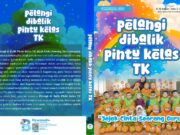Oleh: M. Aris Munandar*
Istilah agraria secara etimologis berasal dari bahasa Latin yakni ager yang berarti sebidang tanah (bahasa Inggris acre). Kemudian bahasa latin aggrarius memiliki arti “yang ada hubungannya dengan tanah, pembagian atas tanah terutama tanah-tanah umum, bersifat rural”. Sedangkan istilah reforma memiliki arti “perombakan”, mengubah atau menyusun, membentuk kembali sesuatu untuk menuju perbaikan. Reforma Agraria merupakan sebutan dalam bahasa Spanyol.
Perubahan konsep agraria melalui reforma agraria seharusnya lebih mementingkan kehidupan masyarakat kecil khususnya masyarakat hukum adat yang merupakan tergolong dalam masyarakat minoritas di Indonesia. Sebagaimana tujuan dari reforma agraria yakni menolong rakyat kecil, mewujudkan keadilan, dan meniadakan atau setidak-tidaknya mengurangi ketidakmerataan pembagian hak.
Reformasi agraria pada prinsipnya diperlukan dalam rangka menciptakan perubahan dalam sistem hubungan korespondenasi sosial ekonomi kemasyarakatan khususnya bagi masyarakat pedesaan. Sebagaimana Indonesia yang tergolong dalam agraris tradisional (feudalistik, non kapitalistik, atau natural economi) kemudian akan menuju pada struktur masyarakat yang terintegrasi pada pilar-pilar ekonomi secara nasional sehingga lebih produktif serta keadilan, dan kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi secara utuh.
Berkenaan dengan reforma agraria, bahwa Indonesia memiliki struktur masyarakat yang komunal dan multikultural salah satunya adalah dengan adanya komunitas masyarakat hukum adat yang mempunyai prinsip kehidupan sangat tradisional. Keadaan masyarakat hukum adat saat ini tidak lagi sama dengan masa-masa sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Pada era sekarang, ujian terbesar masyarakat hukum adat ialah adanya badan-badan usaha yang sewaktu-waktu mampu mengakuisisi lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat hukum adat itu secara turun-temurun.
Pada banyak kasus, sengketa hak menjadi persoalan utama dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Mulai dari sengketa hak atas lahan hingga pada penggusuran permukiman masyarakat adat secara paksa oleh badan-badan usaha tertentu. Pergolakan ini tentunya membutuhkan suatu reformasi dalam perlindungan hak terhadap masyarakat hukum adat itu. Hak adat atau hak ulayat merupakan salah satu hak yang menjadi muatan konstitusi khususnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang secara tekstual mengakui keberadaan hukum adat. Lebih lanjut dalam UUPA juga diatur terkait hak ulayat pada Pasal 3 dan Pasal 5 yang berbunyi:
a) Pasal 3
“Dengan menginat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.
b) Pasal 5
“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.
Regulasi di atas mencerminkan bahwa pengaturan hak ulayat atau hak adat di Indonesia adalah suatu hal yang utama bahkan tetap diakui keberadaannya sampai saat ini. Dengan adanya pengakuan itu maka sudah seyogyanya hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tersebut menjadi cikal bakal terwujudnya reforma agraria. Pengalaman yang panjang dalam aspek agraria di Indonesia juga menjadi landasan historis dalam digalakkannya gerakan reforma agraria tersebut.
Secara spesifik, rasionalisasi terhadap perlunya reforma agraria ialah mencakup 5 (lima) aspek penting, diantaranya:
1) Aspek hukum, yakni demi terciptanya kepastian hukum mengenai hak-hak rakyat atas tanah, terutama lapisan bawah dan terkhusus bagi rakyat petani;
2) Aspek sosial, yakni demi terwujudnya keadilan, struktur agraria yang relative merata akan dirasakan lebih adil, sehingga keresahan dan kemungkinan konflik di bidang agraria dapat dihindarkan;
3) Aspek politik, yakni demi terjaminnya stabilitas, struktur agraria yang adil akan meredam keresahan yang pada suatu waktu dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
4) Aspek psikologis, yakni terciptanya suasana social euphoria dan family security (istilah yang dikemukakan oleh A.T. Mosher) yang sedemikian rupa sehingga para petani dan buruh tani menjadi termotivasi untuk mengelola usaha taninya dengan lebih baik lagi;
5) Aspek ekonomi, yakni bahwa semua pada saatnya dapat menjadi sarana awal untuk terciptanya peningkatan produksi.
Menurut Chonchol, berpandangan bahwa rationale reforma agraria ialah untuk membebaskan masyarakat pertanian dari kungkungan sistem penguasaan tanah feodal-tradisional dan dengan demikian memberikan kesempatan berkembang bagi para pemilik tanah dengan menggunakan mekanisme persaingan usaha. Pandangan dari Chonchol itu menggambarkan bahwa keadilan itu dilihat dari aspek peluang usaha yang setara. Kemudian pada masa selanjutnya yang bermain ialah takdir dan nasib masing-masing (hukum alam).
Penulis menambahkan bahwa aspek dalam mendorong untuk dilakukannya reforma agraria adalah aspek kebudayaan. Yakni krisis yang terjadi Indonesia saat ini ialah terkikisnya kebudayaan dalam menghargai setiap hak yang dimiliki oleh komunitas sosial khususnya bagi hak adat. Terkikisnya hak ini disebabkan oleh hilangnya marwah budaya hukum dalam berbagai kalangan khususnya bagi badan-badan usaha yang secara prinsipiel hanya mengedepankan profit atau pendapatan ketimbang mendahulukan hak-hak adat yang telah dijamin secara konstitusional. Sebagai contoh adalah adanya sengketa lahan yang sering kali menjadi persoalan dalam aspek agraria. Terkadang masyarakat adat mengalami diskriminasi sebagai kaum minoritas atau marginalisasi masyarakat hukum adat. Persoalan seperti inilah yang kemudian akan menjadi corong terciptanya reforma agraria.
Hak adat sebagai corong reformasi agraria adalah sebuah konsep yang fundamental. Prinsip-prinsip pengelolaan hutan dan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat sangatlah bersesuaian dengan asas persatuan dan kesatuan termasuk asas kemanfaatan dan keberlanjutan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya terkait prinsip pengelolaan hutan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Kajang.
Penjaminan hak ulayat merupakan prospek utama yang mesti dijalankan oleh setiap roda pemerintahan dalam menunjang terciptanya keadilan agraria bagi segala kalangan masyarakat Indonesia sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dalam mengelola dan memanfaatkan setiap lahan yang ada. Dengan demikian tidak akan ada lagi hak yang didiskriminasi suatu pihak. Disinilah peran negara untuk menjamin segala kesejahteraan umum dan kesejahteraan khusus dalam hal ini masyarakat hukum adat diseluruh nusantara.
*) Penulis adalah Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Daerah Makassar Periode 2019-2020