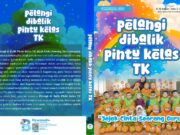Oleh: Muh. Chairul Sahar*
Kota Makassar yang sering digambarkan sebagai kota dunia beberapa hari ini berubah menjadi ruang mencekam yang penuh kekhawatiran. Di tengah Gedung yang menjulang tinggi muncul sekelompok orang tak dikenal (OTK) dengan lantangnya berteriak mencari “Orang Palopo” sembari membawa senjata tajam, busur dan spanduk undangan perang terbuka. Ironisnya situasi ini terjadi di dalam kampus yang semestinya menjadi benteng akal sehat dan ruang pembentukan nilai moral namun justru berubah sebagai arena teror.
Apa yang terjadi bukan sekadar ancaman dan intimidasi sepele melainkan gejala sosial yang sepertinya telah mengakar dalam tubuh mahasiswa. Almamater yang semestinya menjadi simbol dari spirit intelektual dan gerakan kolektif yang universal justru dibaliknya tersembunyi topeng-topeng identitas sempit yang sewaktu-waktu dapat muncul dan memantik ketegangan. Ketika loyalitas terhadap simbol keberpihakan kelompok lebih kuat daripada sebagai insan akademik, maka mahasiswa akan kehilangan makna dan kampus berubah menjadi panggung lakon kekerasan yang terus diwariskan. Lantas menjadi pertanyaan besar apakah pendidikan tinggi masih berfungsi sebagai ruang transformasi sosial?
Warisan Konflik dan Gagalnya Identitas Baru
Konflik berbasis identitas seperti kedaerahan pada mahasiswa bukanlah fenomena yang spontan tetapi merupakan warisan sosial yang kerapkali tak dikritisi. Mahasiswa baru yang hadir dengan “kepolosan” yang semestinya dikenalkan nilai akademis dan keilmuan justru kerap dibentuk dengan doktrin melanjutkan loyalitas pada kelompok yang lebih sempit. Hal ini menjadi pemicu awal dari banyaknya mahasiswa yang gagal untuk merekonstruksi identitas sebagai seorang insan intelektual.
Kampus yang semestinya menjadi ruang lahirnya manusia yang berfikir Merdeka justru kerapkali membiarkan keberlanjutan dari identitas lokal yang eksklusif. Olehnya, identitas sebagai bagian dari komunitas akademik gagal terbentuk. Ruang yang seharusnya mendewasakan nalar namun justru fanatisme tumbuh subur. Akibatnya, teror, intimidasi bahkan kekerasan menjadi ekspresi yang kerap dianggap sah.
Meminjam kacamata Marx, kekerasan yang terjadi mencerminkan konflik sosial yang bersifat struktural. Mahasiswa bukan hanya menjadi homo akademikus tetapi sekaligus mengambil lakon sebagai aktor dalam pertarungan sosial yang lebih luas, saling berebut pengaruh, representasi kekuasaan bahkan sumber daya. Ketika ruang organisasi dan pengaruh dikuasai oleh kelompok tertentu maka benturan antarkelompok seperti kedaerahan menjadi bentuk resisten dan ekspresi ketimpangan yang ada. Loyalitas dan solidaritas kelompok menjadi alat untuk mengonsolidasikan kekuatan bukan lagi menjadi ruang untuk saling belajar dan berdialektika. Konflik bahkan kekerasan seringkali dianggap sah ketika menjadi bagian dari strategi untuk mempertahankan posisi. Sehingga kampus yang semestinya menjadi ruang yang inklusif dan netral justru menjadi tempat reproduksi ketimpangan sosial yang lebih besar.
Konflik dalam tubuh mahasiswa menjadi cermin dari situasi Anomie, istilah yang diperkenalkan Emil Durkheim dalam Suicide (1897), yaitu sebagai bentuk dari kegagalan masyarakat (kampus) untuk membangun suatu norma kolektif yang menyatukan segala perbedaan. Mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang budaya yang sangat beragam tidak memegang suatu nilai bersama sebagai bentuk penyatuan. Sehingga setiap individu akan kembali pada nilai lama yang dipegang, celakanya nilai ini seringkali membentuk loyalitas terhadap kedaerahan, pembenaran atas balas dendam dan kecurigaan terhadap yang berbeda. Dalam masyarakat modern semestinya solidaritas dibangun secara organik dengan kerjasama antar individu berbeda namun tetap terus terhubung secara fungsional, hal ini yang semestinya harus terwujud dalam dunia kampus yaitu interaksi plural yang produktif bukan pada permusuhan dan dendam.
Kampus dan Mahasiswa Mesti Kembali pada Fitrahnya
Situasi ini bukan hanya mengancam tubuh dan jiwa mahasiswa tetapi yang lebih menakutkan adalahnya runtuhnya nalar. Mahasiswa yang semestinya mengambil peran sebagai agent of change justru terjebak dalam konflik identitas yang begitu sempit. Hal ini dapat menjadikan gerakan mahasiswa kehilangan daya transformasi karena perjuangan bukan lagi berdasar pada nilai dan ideologi tetapi justru pada solidaritas terhadap identitas kelompok.
Kampus sebagai laboratorium peradaban perlu kembali pada esensi fundamentalnya sebagai ruang terbentuknya karakter dan kemanusiaan. Universitas semestinya tidak hanya mengandalkan kurikulum formal tetapi harus lebih serius dalam merancang dan membentuk ekosistem yang mendorong penyatuan mahasiswa dan menghilangkan sekat latar belakang identitas. Karena tanpa upaya sadar untuk menumbuhkan nilai-nilai kolektif yang inklusif maka kampus hanya akan menjadi wajah yang cerdas namun rapuh secara sosial.
Konflik identitas yang terus terjadi secara berulang menjadi warning untuk semua pihak baik kampus, pemerintah, mahasiswa dan masyarakat. Harapan kepada mahasiswa untuk menjadi motor penggerak perubahan masa depan akan pupus jika sejak awal tidak mampu untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara-cara yang beradab. Kelahiran intelektual progresif dari ruang-ruang kuliah hanyalah ilusi jika dalam tubuh mahasiswa tumbuh kultur dan warisan dendam dan glorifikasi kekerasan. Sudah semestinya mahasiswa menolak untuk menjadi pewaris konflik, menolak untuk terus menggunakan “topeng identitas” yang saling membatasi. Dan yang paling penting adalah berani untuk menempuh yang lebih sulit yaitu jalan berfikir dan berdialaog yang menyatukan. Karena “Mahasiswa” bukan sekedar status semata tetapi gelar yang penuh makna, harapan dan beban moral.
*) Penulis adalah Ketua Umum PK IMM Fakultas Teknik Unhas