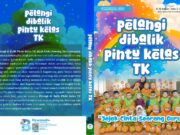Oleh: Muh. Chairul Sahar*
Narasi tentang pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia selalu diwarnai oleh optimisme. Slogan seperti swasembada, kemandirian pangan, hilirisasi pertanian dan desa yang berdaya menjadi jargon yang berulang dalam pidato para pejabat pemerintah. Petani selalu disebut sebagai “pahlawan pangan” yang menjadi simbol keberlanjutan hidup bangsa yang selalu disanjung. Namun, ketika mengunjungi Desa Mokantarak, wajah pertanian yang ada sangat berbeda dari narasi besar itu. Di tepi laut, pada hamparan tanah yang sederhana, kita menyaksikan perempuan-perempuan paruh baya yang hampir memasuki masa renta bahkan sebagian besar telah memiliki cucu, masih sangat semangat bekerja tanpa lelah. Dengan tangan yang keriput tapi cekatan dalam mengolah garam yang hanya bermodalkan tanah, air laut dan peralatan sederhana.
Di balik butiran garam yang sering kita taburkan ke masakan atau yang kadang tersisa begitu saja di meja makan, terdapat kisah yang panjang tentang kerja keras dan ketahanan hidup. Rantai produksi yang menghubungkan desa dan kota begitu panjang sehingga sering kali menghapus jejak mereka yang berada di awal proses. Mereka yang bekerja keras dalam memproduksi justru kerap menerima keuntungan paling kecil, sementara pihak yang berada di hilir rantai mendapat nilai tambah yang jauh lebih besar. Fenomena ini bukan hanya persoalan produksi saja, tetapi juga menunjukkan ketimpangan struktural yang membentuk gap besar antara siapa yang diuntungkan dan siapa yang terpinggirkan. Garam, bumbu dapur yang tampak sangat sederhana, namun ternyata adalah cermin dari relasi sosial yang lebih luas dan kompleks.
Tubuh Sosial yang Rapuh
Teori Struktural Fungsional mengibaratkan masyarakat sebagai satu tubuh manusia. Setiap bagian memiliki fungsi tersendiri yang saling melengkapi demi menjaga keseimbangan dan kesinambungan sistem sosial. Petani garam di Mokantarak ialah salah satu organ vital dalam tubuh ini walaupun sangat terlihat begitu sederhana. Bukan hanya memproduksi garam untuk kebutuhan rumah tangga lokal, tetapi juga menopang rantai pangan yang lebih besar, dari industri makanan hingga konsumsi rumah tangga di berbagai wilayah. Keberadaan ini memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi yang kerap kali peran ini tak disadari oleh konsumen di kota.
Namun kondisi yang ada, tubuh sosial ini tengah mengalami keretakan. Teknologi yang digunakan para petani masih sangat sederhana, sementara kebijakan pemerintah lebih banyak menguntungkan industri besar dibanding produsen kecil. Mereka yang bekerja di desa berada dalam posisi yang lemah, tanpa akses terhadap pasar yang adil dan alat modern yang dapat meningkatkan produktivitas. Dengan kondisi seperti ini maka secara otomatis tubuh sosial mengalami disfungsi. Hal ini dapat berpengaruh besar dimana lemahnya satu elemen dalam sistem dapat berefek dan mengguncang kestabilan nasional.
Talcott Parson menekankan bahwa keseimbangan sosial (equilibrium) hanya dapat tercapai jika setiap elemen sistem diberi peran dan penghargaan yang proporsional. Sehingga ketika satu bagian melemah, maka tanggung jawab negaralah untuk memulihkan fungsi tersebut agar dapat harmoni kembali. Bagi para petani garam di Mokantarak, kehadiran pendamping ahli, penyediaan alat yang lebih efisien, dan kebijakan harga yang adil bukan sekadar bantuan teknis, tetapi sebagai bentuk pengakuan atas peran vitalnya dalam tatanan masyarakat. Jika bagian ini terus diabaikan, maka gangguan pada satu organ akan berdampak dan turut melemahkan tubuh sosial secara keseluruhan.
Keringat Perempuan yang Tak Diakui
Hal yang paling menggugah hati pada kelompok petani garam di Mokantarak adalah kenyataan bahwa mayoritas petani ini adalah perempuan yang telah berumur. Mereka bekerja dari pagi hingga sore, di bawah teriknya matahari dan memikul beban fisik yang berat, sambil tetap mengurus rumah tangga bahkan merawat anak dan cucu. Fenomena ini memperlihatkan betapa beratnya beban ganda yang dipikul oleh perempuan pedesaan. Tidak hanya bekerja untuk menghasilkan garam sebagai salah satu sumber ekonomi keluarga, tetapi juga secara bersamaan memikul tanggung jawab reproduktif untuk memastikan keberlangsungan hidup generasi berikutnya.
Mirisnya, kerja keras ini sering kali tak terlihat dan tak diakui. Mereka jarang ternotice dan tercatat dalam statistik resmi atau perencanaan konsepsi pemajuan. Narasi besar tentang ketahanan pangan sering menghapus identitasnya, seakan garam yang dikonsumsi lahir begitu saja tanpa jerih payah yang menyakitkan. Persoalan ini bukan sekadar soal kemiskinan belaka saja, tetapi juga soal relasi kekuasaan yang menempatkan perempuan di posisi paling rentan.
Ketika anak muda khususnya laki-laki, memilih untuk meninggalkan desa dan bekerja di kota, maka secara langsung beban kerja semakin menumpuk di pundak perempuan desa khususnya yang telah paruh baya. Mereka yang seharusnya menikmati masa tua justru mengambil peran besar dalam produksi garam. Jika kebijakan pembangunan hanya berbicara tentang teknologi dan produktivitas tanpa mempertimbangkan realitas gender, maka ketimpangan ini akan terus berulang. Mendorong modernisasi kepada para petani memang penting, namun yang lebih mendasar adalah bagaimana memberikan pengakuan sosial. Mengakui bahwa perempuan adalah aktor dalam produksi pangan berarti membuka ruang untuk petani perempuan memiliki suara dalam pengambilan keputusan.
Garam yang kita taburkan di masakan sehari-hari sesungguhnya adalah hasil dari keringat perempuan yang tak pernah terdengar suaranya. Mengangkat perjuangan mereka berarti menuntut keadilan gender dalam pembangunan, sehingga penting untuk memastikan bahwa perempuan tidak lagi menjadi pilar tersembunyi yang menopang sistem tanpa dihargai.
Harapan yang Sederhana
Mendengar aspirasi para petani garam di Mokantarak yang sebenarnya hanya membawa harapan yang sangat sederhana. Bukan pada program yang rumit atau retorika besar tentang ketahanan pangan. Namun hanya ingin pendamping ahli yang bisa memandu mereka meningkatkan teknik produksi tanpa menghilangkan kearifan lokal, alat yang lebih modern agar pekerjaan mereka lebih efisien dan tidak terlalu membebani tubuh, serta akses pasar yang memberikan harga layak untuk hasil kerja kerasnya.
Pemenuhan kebutuhan ini berarti memperkuat organ vital dalam tubuh sosial untuk memulihkan keseimbangan yang rapuh dan mencegah disfungsi yang lebih besar. Langkah ini adalah salah satu bentuk keadilan gender yang nyata. Dimana perempuan tidak lagi dipandang sebagai tenaga kerja murah, tetapi menjadi bagian dari subjek pembangunan yang memiliki hak, suara, dan kendali atas hidup sendiri.
Petani garam Mokantarak mengajarkan bahwa pembangunan sejati bukanlah sekadar angka pertumbuhan ekonomi atau target produksi belaka. Pembangunan sejati adalah tentang menghargai kerja yang selama ini tak terlihat, keringat yang jarang disebut, dan tangan-tangan yang diam menopang kehidupan masyarakat. Sehingga jika terus menerus hanya memandang petani garam sebagai angka dalam laporan produksi, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk memahami makna sesungguhnya dari garam.
Garam didapur bukan hanya tentang rasa asin di lidah, tetapi juga rasa kemanusiaan yang menyatukan. Para petani garam menjadi satu penopang penting yang menjaga sistem sosial tetap berjalan. Mereka juga sebagai pahlawan tersembunyi yang menghadapi beban ganda dengan namu dengan keberanian yang luar biasa. Sehingga lebih jauh kita mesti melihat garam bukan hanya persoalan teknis produksi, tetapi juga persoalan struktur sosial dan relasi gender yang saling terkait.
Jika negara benar-benar ingin membangun ketahanan pangan yang berkeadilan, maka langkah awal mesti dimulai dari desa, dari lahan-lahan kecil di tempat yang jauh. Dari tangan-tangan perempuan desa yang bekerja dalam diam, negara dapat belajar bahwa keadilan sosial tidak lahir dari slogan saja, tetapi dari keberanian untuk mengakui, menghargai, dan mendukung kaum yang selama ini berada di garis depan kehidupan. Garam tidak hanya menjaga rasa pada makanan kita, tetapi juga rasa keadilan dalam kehidupan sosial kita.
*) Penulis adalah Ketua Umum PK IMM Teknik Unhas