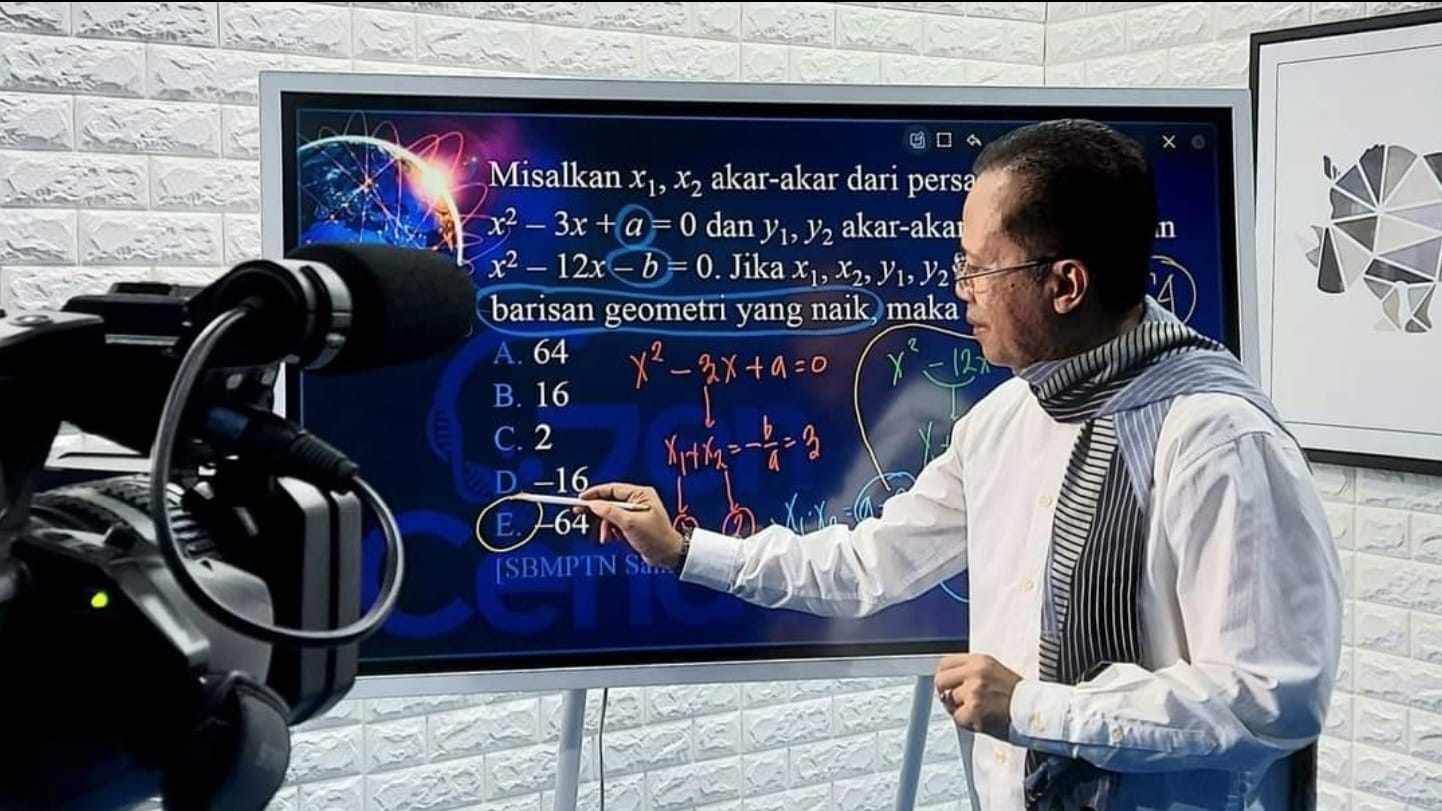Oleh : A M Iqbal Parewangi
(Pemerhati Pendidikan & Praktisi Manajemen)
Makhluk AI paling nyaring disebut di panggung global kini: dipuja sebagai mesin keajaiban, sekaligus dicurigai sebagai ancaman besar bagi pekerjaan manusia. Di balik hiruk-pikuk itu, pertanyaan sejatinya lebih mendalam: akankah kita sekadar gentar dan tertinggal, atau justru menjadikannya alat untuk melompat lebih jauh?
Catatan singkat ini mengajak bercermin pada jejak revolusi industri, menyimak narasi publik tentang AI, hingga merasakan denyut tantangannya. Untuk menghindari sesat nalar, anak saya Avo Avecienna—dari Teknik Informatika LMU Munchen, Jerman—menafasi catatan ini dengan gagasan sederhana namun fundamental: berani bekerja lebih cerdas bersama AI.
ANCAMAN ATAU KENISCAYAAN?
Sejak kehadirannya dalam percakapan publik, kecerdasan buatan (AI) semakin sering diposisikan sebagai ancaman besar bagi masa depan dunia kerja. Narasi yang berulang—baik dalam laporan media maupun hasil riset—menunjukkan angka potensi pengangguran massal akibat otomatisasi.
Laporan McKinsey Global Institute (2017), misalnya, memperkirakan 75–375 juta pekerja di seluruh dunia (3–14%) perlu beralih pekerjaan dan meningkatkan keterampilan pada 2030, bergantung skenario otomasi.
Sementara itu, World Economic Forum dalam Future of Jobs Report (2025) melaporkan hasil survei pemberi kerja bahwa 39% keterampilan diperkirakan terdisrupsi dalam lima tahun ke depan—turun dari 44% pada survei 2023—yang didorong oleh kombinasi AI dan teknologi lainnya, pergeseran ekonomi, dan transisi hijau.
Narasi ancaman ini juga kuat menggema di Indonesia. Menimpali kegalauan Jokowi atas data McKinsey soal AI, saat itu masih presiden, kepala Bappenas menyatakan perlu strategi mitigasi serius untuk mencegah gelombang pengangguran akibat penetrasi AI di pasar kerja nasional (NusantaraTV, 2025).
Bahkan seorang Wakil Menteri jebolan universitas terkemuka dunia tidak luput dari retorika serupa: mengumbar peringatan skeptis bernuansa sinis, seolah AI hanya akan melemahkan daya pikir mahasiswa sehingga harus diwaspadai.
Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan betapa narasi tentang AI seringkali terjebak dalam alarmisme “Alien Intelligence” yang melemahkan kepercayaan diri generasi, ketimbang membangun optimisme “Artificial Intelligence” yang membuka peluang transformasi.
NARASI “ANCAMAN AI” MENGERDILKAN
Ada bahaya serius jika kita hanya terpaku pada sisi ancaman. Narasi “AI menggantikan manusia” sering kali berlebihan, karena tidak membedakan antara “pekerjaan” dan “tugas”.
AI memang menggantikan tugas-tugas yang repetitif, administratif, dan berbasis pola, tetapi itu justru membuka ruang baru bagi manusia untuk melakukan kerja yang lebih kreatif, integratif, dan bermakna. Alih-alih menghapuskan manusia, AI justru mendorong kita untuk bertransformasi.
Fenomena historis serupa sudah pernah terjadi. Revolusi Industri abad ke-18 dan ke-19 sempat memantik ketakutan besar akan hilangnya pekerjaan manual akibat mesin uap. Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa ketakutan itu lebih banyak menghantui mereka yang menolak bertransformasi.
Di Eropa Barat, adopsi mesin dan tata niaga baru justru melahirkan lonjakan produktivitas, penciptaan profesi baru, dan penguatan peran manusia dalam ranah yang tak bisa digantikan mesin: desain, strategi, manajemen, seni, dan nilai-nilai kemanusiaan (Brynjolfsson & McAfee, 2014).
Sebaliknya, mereka yang terlambat merespons arus perubahan mengalami kemunduran. Qing Tiongkok, misalnya, mencoba gerakan Self-Strengthening (1860-an) tetapi membatasi adopsi industri hanya untuk militer dan galangan. Tanpa reform institusional, tenaga teknis, dan integritas manajerial, upaya itu kandas di tengah fragmentasi dan korupsi (Elman, 2005).
Kekaisaran Utsmani pun terjebak pada resistensi internal dan capitulations yang menggerus kemandirian fiskal, sehingga modernisasi industrinya hanya setengah hati (Britannica, Ottoman Empire, 2025).
Rusia Tsaris lebih lama lagi tertahan oleh sistem perbudakan tanah (serfdom) hingga akhir abad ke-19, baru berlari lewat “era Witte”—namun tetap tertinggal dari Inggris dan Jerman (Britannica, Russia, 2025).
Bahkan India, yang pada 1750 menyumbang seperempat output industri dunia, mengalami de-industrialisasi drastis di bawah kolonialisme Inggris hingga pangsanya merosot menjadi hanya sekitar 2% pada 1900 (Clingingsmith & Williamson, 2008).
Dengan demikian, sejarah revolusi industri memperlihatkan pola yang jelas: bangsa yang berani merangkul teknologi baru dengan disertai reformasi institusional menuai kemajuan, sementara yang menolak, ragu, atau hanya melangkah setengah hati justru terperosok dalam ketertinggalan.
Maka, ketakutan terhadap AI hari ini sesungguhnya hanyalah gema masa lalu dalam wajah baru. Seperti mesin uap di abad silam, AI akan menjadi batu pijakan bagi mereka yang mau bertransformasi—tetapi sekaligus batu sandungan bagi mereka yang menolak arus sejarah.
LEBIH CERDAS BERSAMA AI
Alih-alih melihat AI sebagai “pengganti”, lebih tepat memandangnya sebagai “pengganda kecerdasan” (intelligence amplifier). Dalam banyak sektor, keunggulan nyata bukan terletak pada “AI murni” atau “manusia murni”, melainkan pada simbiosis keduanya.
Seorang arsitek yang menguasai generative design berbasis AI dapat mengeksplorasi ribuan kemungkinan desain bangunan dalam hitungan menit, lalu memilih dan menyempurnakan hasilnya dengan mempertimbangkan estetika, budaya, fungsi, dan konteks lokal—sesuatu yang tidak dapat diputuskan AI semata.
Seorang dokter yang menggunakan AI dalam diagnosis intraoperatif tumor otak dapat memperoleh akurasi tinggi—sekitar 94,6% pada studi Nature Medicine (2020) yang menggabungkan citra stimulated Raman histology dengan deep learning—namun keputusan empatik tentang terapi terbaik tetap lahir dari interaksi manusiawi antara dokter dan pasien (Hollon dkk., 2020).
Demikian pula, ahli hukum yang memanfaatkan AI untuk menyaring ribuan dokumen kasus akan menemukan konstruksi hukum lebih cepat (Grossman & Cormack, 2011), tetapi
makna keadilan substantif tetap menuntut kepekaan etis dan nilai-nilai kemanusiaan.
Ustadz dan da’i yang memakai AI sebagai alat dakwah digital dapat menjangkau audiens global dengan cepat (Bunt, 2018), tetapi penyadaran spiritual yang menyentuh hati tetap membutuhkan kehadiran manusia sebagai saksi hidup nilai iman (Campbell, 2017).
Konsultan bisnis yang mengintegrasikan analitik AI akan menemukan pola-pola pasar lebih presisi, tetapi keputusan strategis tetap memerlukan intuisi, pengalaman, dan keberanian mengambil risiko (Wilson & Daugherty, 2018).
Singkatnya, AI membuat manusia bekerja lebih cerdas, bukan tergantikan. Model ini mengingatkan saya pada centaur model—istilah yang lahir dari dunia catur, ketika grandmaster Garry Kasparov menemukan bahwa kombinasi manusia + mesin dapat mengalahkan mesin murni maupun manusia murni (Kasparov, 2017).
Inilah paradigma baru dunia kerja abad ke-21: kecerdasan kolektif yang lahir dari kolaborasi manusia dan AI.
BIJAK, BUKAN MENOLAK
Ada dua kesalahan bersifat diametral yang sering terjadi: menolak AI sama sekali, atau membiarkan AI bekerja tanpa kendali. Keduanya naif dan fatal.
Pertama, menolak AI sama saja menutup mata dari arus sejarah. Ketika dunia sudah memanfaatkan AI untuk mempercepat riset medis, memperkuat keamanan siber, dan mendorong efisiensi energi, maka sikap anti-AI hanya akan menjerumuskan masyarakat pada keterbelakangan (Brynjolfsson & McAfee, 2014).
Kedua, menyerahkan segalanya pada AI tanpa etika dan pengendalian manusia akan memunculkan risiko serius: bias algoritmik, penyalahgunaan data, disinformasi, hingga degradasi nilai kemanusiaan (Crawford, 2021).
Karena itu, kepemimpinan publik harus bergerak melampaui wacana ancaman. Tugas negara, institusi, dan komunitas adalah membangun kesadaran dan keterampilan baru agar warga mampu bekerja lebih cerdas dengan AI. Pendidikan dan pelatihan berbasis AI literacy harus diarusutamakan, kurikulum disesuaikan, dan regulasi disusun agar AI dipakai secara etis dan inklusif.
Di sinilah peran spiritualitas dan nilai kemanusiaan menjadi jangkar. AI mampu mengolah data dalam jumlah tak terbatas, tetapi tidak mampu memahami makna terdalam dari keadilan, kasih sayang, atau pengorbanan. Justru di titik inilah manusia menemukan martabatnya: menjadi makhluk yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak.
Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah:30, manusia ditetapkan sebagai khalifah di bumi—bukan karena kecepatan komputasi, melainkan karena kapasitas moral dan kesadarannya.
GESER NARASI
AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi akan mengguncang mereka yang tidak bersiap. AI hanya menjadi ancaman bagi mereka yang enggan lebih cerdas: enggan bertransformasi, enggan belajar ulang, dan enggan membangun kecerdasan kolektif.
Sebaliknya, bagi yang mau menguasai, mengendalikan, dan mengintegrasikannya secara bertanggung jawab, AI justru menjadi jembatan menuju cara kerja yang lebih cerdas, produktif, dan bermakna.
Narasi besar kita harus bergeser: bukan sekadar meratapi “ancaman pengangguran akibat AI”, tetapi membangun kesadaran transformatif: bekerja lebih cerdas dengan AI. Kenaifan terbesar bukanlah ketakutan terhadap AI, melainkan menutup diri dari peluang besar yang ditawarkannya.
AI tidak punya jiwa, dan justru karena itu ia menantang kita untuk bekerja lebih cerdas dengan akal, hati, dan iman.
Salam takzim,