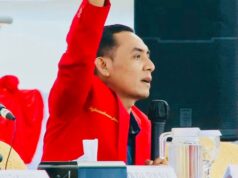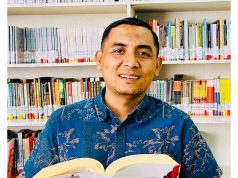Oleh : Fajlurrahman Jurdi*
Pengadilan adalah tempat terakhir untuk merajut kehidupan kolektif, karena tempat inilah yang memberi kepastian atas nota keadilan yang dituntut oleh masyarakat karena social contract. Negara semula tiada, lalu ada, karena perjanjian. Semula perjanjian itu disebut “pactum unionis”, hanya sepihak saja. Klan-klan politik atau masing-masing individu menyerahkan seluruh hak mereka kepada seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan “primus interpares”, tanpa ada umpan balik kewajiban. Perjanjian dalam skema ini melahirkan negara totaliter. Namun kemudian diperbaiki oleh Locke, bahwa perjanjian itu tidak saja pactum unionis, tetapi juga pactum subjectionis. Pada perjanjian kedua inilah hak, kewajiban, rule of the game, atau batas-batas hak mulai diperkenalkan.
Maka ketika kekuasaan dipisah kedalam la puissance legislative, la puissance executive, dan la puissance the juger, kehendak kekuasaan yang semula di satu tangan dihentikan. Konsep e’tat ets moi, misalnya, berhenti, meskipun slogan ini ditumbangkan oleh kutukan rakyat Prancis di sepanjang jalan dengan teriakan yang tak terlupakan, liberte, egalite dan fraternite.
Orang-orang yang berkuasa harus mulai berhitung, sebab kekuasaan yang terpisah ke dalam tiga tangan tak lagi dikendalikan oleh seorang monark yang sifatnya absolut. “The juger” menjadi wasit yang akan menegakkan hukum atas perilaku siapapun, baik mereka yang berkuasa maupun mereka yang tak punya kuasa. Maka abad ini sebenarnya adalah abad dimulainya masa dibangunnya rechtstaat, meninggalkan bangkai busuk machtstaat, yang berlumuran darah kekerasan, perbudakan dan pengekangan pada hak-hak individu.
Ketika hukum dikonseptualisasi sebagai kehendak publik yang bersifat imperatif, ia sebenarnya menjadi pedang bermata dua. Jika ditegakkan akan menyakiti yang satu dan memberi kenyamanan bagi yang lain. Tetapi ada value yang hendak dijamin eksistensinya. Saat negara dibentuk, alat-alat kelengkapan negara bekerja menurut logika publik, dan logika publik yang dimaksud sebenarnya instrument hukum yang dibentuk dengan cermat.
Norma hukum hanya satu diantara sekian banyak norma, seperti norma agama, norma moral, norma kesusilaan, norma kesopanan atau norma lainnya. Prinsip-prinsip dasar norma ini adalah mengatur tentang kebaikan. Misalnya, norma moral melarang mencuri. Pada saat yang sama, semua agama dapat dipastikan melarang mencuri, kesusilaan juga demikian. Tetapi jika orang mencuri, yang ia langgar adalah norma moral dan norma agama. Sanksinya dikucilkan atau dihukum menurut konsep dan standar agama. Jika demikian, bisa terjadi kontradiksi-kontradiksi. Bila seorang muslim mencuri harta seorang Kristen, hukum agama manakah yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalahnya?. Dalam islam, hukum bagi si pencuri adalah potong tangan, lalu dalam Kristen apa hukumannya?. Moral juga tidak imperatif, hanya pengucilan dan sebagainya dari masyarakat. akibatnya, bisa terjadi kontradiksi dalam masyarakat.
Lalu negara hadir dan memiliki hukum. Hukum ditegaskan oleh apparatus, yakni polisi, jaksa hakim. Dalam hal ini “the juger” sebagai “penjagal” perilaku tiap orang dengan mendasarkan pada norma hukum yang telah dibentuk di bawah payung besar yakni perjanjian sosial. Dalam hal ini, proses hukum tidak melulu berada pada urat nadi hukum tertulis seperti undang-undang, tetapi juga living law, hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
Atas alasan ini, hakim diminta untuk “menyelami” suara-suara perih dari pinggir. Dalam bahasa undang-undang, hakim harus memutus perkara berdasarkan keyakinan yang ia punya. “Iman” hakim atas satu perkara sangat penting, mengingat palu yang ia ketuk menentukan hidup-matinya jiwa atau raga seseorang. Hak orang dicabut, termasuk hak untuk hidup. Bila salah menyelami suara-suara perih yang berdetak diluar lembaga Peradilan, hakim bisa saja menjatuhkan putusan yang keliru dan menyebabkan terjadinya kedholiman, bila ia tak melakukan perenungan dan meluruskan ijtihadnya.
Karena hakim memutus berdasarkan keyakinannya, maka bisa saja hakim memutus diluar dari yang dituntut oleh Jaksa. Mungkin hakim menganggap bahwa tuntutan jaksa tidak sesuai dengan hasil perenungan dan iman yuridis sang hakim. Hakim minimal mendasarkan putusan nya pada tiga hal sebagaimana kata tuan Gustav, yakni menegakkan keadilan, memberi kepastian terhadap suatu situasi yang turbulen karena suatu kejahatan, dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Hakim memastikan juga power yang dipisahkan bisa saling cek and balance. Eksekutif tidak bisa mengintervensi hakim, legislatif tidak dapat menekan putusan hakim, karena itu, hakim dalam negara hukum adalah manusia merdeka yang hanya mendengarkan “suara batin” nya. Di dalam kesunyian dan bisikan batin inilah hakim menjadi transenden.
Dengan demikian hakim tidak selaku harus merujuk pada nota tuntutan jaksa, tetapi dia dapat mengabaikan itu. Bila hakim memutus diuar dari yang diminta oleh jaksa dan terdakwa, itulah mungkin yang disebut dengan ultra petita, memutuskan diluar dari yang diminta. Meskipun dalam konteks hukum Indonesia, hakim tidak boleh melampaui undang-undang. Dasarnya adalah hati nurani dan iman hakim. Hakim menjadi sentral eksistensinya, karena dia mewakili Tuhan di Bumi dalam menegakkan hukum. Kemandirian dan akal budi hakim harus terus-menerus diasah agar putusan nya mempunyai andil bagi masyarakat beradab.
Dengan kemandirian dan kemerdekaan nya, hakim memberi makna konkrit atas konsep negara hukum. UUD NRI tahun 1945 menegaskan, “Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum”. Negara hukum berarti hukum yang menjadi panglima, hukum yang memegang kendali. Hukum yang berdaulat. Hukum berada di atas segalanya. Artinya hakim menjaga hukum agar selalu menjadi panglima.
Putusan hakim atas kasus BTP adalah merupakan salah satu tanda bahwa Indonesia masih memiliki harapan untuk menjadi negara hukum. Setelah jaksa menuntut hanya satu tahun dan dua tahun percobaan, hakim memutus lain. Artinya iman yuridis hakim tidak seirama dengan iman yuridis jaksa. Dalam hal ini, hakim menyelami suara-suara perih rakyat yang merasa terluka oleh ucapan BTP yang menista agama. Semula ucapaan itu hanya melanggar kesusilaan, atau melanggar norma agama, misalnya tidak boleh mencela kitab suci umat beragama. Tetapi sanksi kedua norma itu tidak tegas, bahkan bila ditegakkan bisa memicu perang semua melawan semua. Antara orang Islam yang meminta BPT diadili dengan non muslim dan sebagian muslim yang mendukung ucapan BTP.
Tetapi negara hadir memberi kepastian dengan hukumnya yang memiliki sanksi impertaif. Jatuhlah palu godam hakim, menghentikkan kekacauan dan memastikan bahwa hukum masih menjadi panglima. Sanksi menimbulkan luka si terhukum dan perasaan puas bagi yang merasa terluka. Tetapi pada dasarnya yang dihukum adalah perbuatan jahatnya, bukan orang nya. Agar perbuatannya tidak diulangi dan yang bersangkutan bisa belajar dari kesalahan-kesalahan nya.
*)Penulis adalah tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin