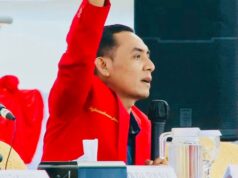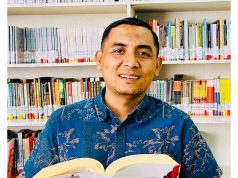Oleh : Fajlurrahman Jurdi*
Saat hakim memeriksa perkara, ada kewajiban “tertulis yang tak terukur” baginya dengan melibatkan iman yang abstrak untuk terlibat dalam urusan konkrit. “Iman yang abstrak” ini disebut dengan “keyakinan hakim”. Meyakini sesuatu adalah soal yang paling tansenden dari subyek. Jika seorang laki-laki mencintai perempuan, biasanya yang ada dalam imajinasinya adalah kecantikan. Atau kadang-kadang juga temannya bertanya; “cantik gak pacarmu?”. Persepsi tentang “cantik” mengandung imajinasi subyek, karena cantik bagi si Polan, tidak sama cara pandangnya dengan si Budi. Akibatnya, cantik bukanlah soal “obyektif” ketika dipandang si subyek yang berbeda, tetapi ia mengikuti “keyakinan” dan “persepsi” subyek.
Hakim adalah “subyek”, sedangkan kasus hukum yang ia periksa berada dalam posisi sebagai “obyek” yang diperiksa. Posisi “obyek” adalah dipandang, dilihat, dianalisa dan dipersepsi. Ada dua elemen yang mempengaruhi subyek, yakni “elemen internal” dan “elemen eksternal”. Pada elemen internal, si subyek dipengaruhi oleh “pengetahuan yang ia miliki, rasa percaya yang ia punya, dan ideology yang melatarbelakangi posisi subyek”. Sedangkan pada elemen eksternal, si subyek dipengaruhi oleh “kejadian atau peristiwa, saksi-saksi atau orang-orang terdekatnya”.
Elemen eksternal bukanlah elemen primer yang mempengaruhi subyek, ia hanya elemen sekunder, karena hanya elemen internal yang dapat menentukan keputusan subyek. Sebagai subyek, hakim adalah merupakan jabatan public, yang secara khusus “memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya”, dan “terhadap perkara yang diajukan tersebut, hakim tidak boleh menolaknya” dengan alasan bahwa hukum belum mengaturnya.
Dalam konteks lain, hakim juga memiliki tugas untuk “menemukan hukum” atau yang dikenal dengan “rechtsvinding”. Tugas penemuan hukum ini berhubungan dengan posisi hakim yang sangat sentral sebagai penegak hukum. Ia berada di hulu, sehingga semua ujung penegakan hukum akan berakhir di pengadilan, dan subyek pemutus di pengadilan adalah hakim.
Kompatibilitas antara “larangan menolak memeriksa dan memutus perkara yang diajukan” dengan tugas “penemuan hukum” tersebut, maka skema rule (aturan) memperkuat posisi hakim dengan meletakkan otonomi subyek untuk menilai, “benar, kurang benar, tidak benar atau tidak benar sama sekali” suatu perkara yang ditangani.
Oleh karena begitu kuatnya posisi hakim sebagai subyek dalam pengadilan, dan jaminan tertulis yang sifatnya terbuka tetapi transenden, maka tak heran kadang-kadnag hakim memutus perkara diluar dari apa yang diminta oleh para pihak. Dalam konteks ini, hakim berperan sebagai subyek bebas yang mandiri dan tentu saja menemukan sesuatu yang diluar dari “kesadaran” para pihak. Putusan “melampaui dari yang diminta” oleh para pihak ini disebut dengan “ultra petita”.
Ultra petita adalah merupakan asas yang menyatakan bahwa; “hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, ia tidak boleh memutus apa yang tidak dituntut atau mememutus melebihi yang diminta”. Larangan untuk hal ini berlaku dalam hukum perdata Indonesia, dimana pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3)Het Herziene Indonesisch Reglement atau yang disingkat dengan HIR. Ketentuan ini pada prinsipnya “melarang hakim sebagai si subyek dalam pengadilan perdata untuk memutus melebihi dari tuntutan”
Tetapi publik berdebat panjang soal apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, karena hakim konstitusi banyak “memutus perkara melebihi dari apa yang diminta”, atau “memutus perkara yang tidak dituntut”. Hakim Konstitusi melanggar prinsip hukum yang melarang hakim untuk memutus perkara diluar dari tuntutan. Putusan ultra petita ini mendapat sorotan luas dari publik. Meskipun demikian, Hakim Konstitusi “mengulang terus” gaya ini. Apabila mereka merasa bahwa ini terkait dengan basis argumentasi konstitusional, hakim akan memutusnya meskipun tidak diminta untuk diputus.
Mahkamah konstitusi adalah merupakan lembaga penjaga konstitusi. Hakim disana memiliki posisi sentral, yakni sebagai “the guardian of the constitution”. Mereka tidak menyelesaikan urusan orang-perorang sebagaimana dalam hukum perdata. Mahkamah konstitusi juga adalah merupakan lembaga peradilan yang putusannya bersifat “final and binding”. Tak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para pihak setelah putusan hakim itu dibacakan. Sedangkan dalam skema hukum perdata, masih terdapat tahapan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara, mulai dari pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi serta kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila tidak puas juga dengan putusan kasasi, instrument hukum menyiapkan upaya hukum ular biasa, yang disebut dengan “peninjauan kembali” perkara apabila terdapat novum (bukti baru) yang kuat.
Meskipun tulisan ini tidak hendak membahas secara khusus mengenai putusan pengadilan perdata atau pengadilan konstitusi, tetapi maksud atau makna eksistensi si subyek yang menjatuhkan putusan “ultra petita”, merupakan refleksi imperatif dari kewajiban hakim yang dinyatakan dalam undang-undang, bahwa; “hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya”, dimana dia berpijak pada kewajiban lain, yakni “menemukan hukum” untuk meyelesaikan perkara yang diperiksa dan diadili. Kewajiban memeriksa dan mengadili perkara tersebut merupakan kewajiban imperatif yang diperintahkan oleh undang-undang, sehingga tak ada alasan lain bagi hakim selain harus menjatuhkan putusan.
Pada konteks inilah, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution yang merupakan lembaga pemutus yang bersifat final dan mengikat terhadap suatu perkara yang menjadi kewenangannya, sehingga diberikan keleluasaan untuk menjatuhkan putusan ultra petita terhadap perkara tersebut.
Karena itu, putusan ultra petita adalah merupakan refleksi “transendental hakim” yang memiliki “kebebasan terikat” untuk menjatuhkan putusan. Kita dapat membayangkan, bahwa hakim harus memutuskan perkara dengan berpijak pada “keyakinan”-nya sebagai alas moral.
*) Penulis adalaha dosen Fakultas Hukum Unhas